Semarang, 7 November 2008
Enak Mana, Reporter atau Narasumber?
Oleh Anindityo Wicaksono
BELAKANGAN ini nama saya sering disebut-sebut sebagai narasumber dalam beberapa media cetak dan online. Ada tiga permasalahan bertemakan budaya dan sosial yang menyertakan pandangan pribadi saya ini: RUU-Pornografi, film nasional, dan ideologi Pancasila dalam momentum Sumpah Pemuda 2008.
Sebenarnya, berita-berita ini awalnya bersumber dari satu media: Kantor Berita Antara Biro Jateng. Reporternya yang menulis, Brando Sinurat, pun kawan kental saya sendiri. Namun, karena memang jaringan kantor berita ini menasional, jadilah warta yang memuat nama saya itu tersebar luas.
Mulai dari Harian Sinar Indonesia Baru (Medan), Harian Pelita, Harian Suara Karya, Institut Perempuan Online, Gatra Online, hingga menjadi pembahasan dalam beberapa blog yang memuat analisis aneka berita. Lantas apa rasanya melihat nama sendiri masuk media? Kaget bin bangga. Selain itu, lucu.
Kok lucu? Ya, saya yang notabene reporter, jurnalis, yang biasa mewawancarai dan menuliskan pendapat para pakar di surat kabar, kini malah muncul di koran sebagai narasumber. Sombong? Tidak juga. Saya cuma jadi lebih paham. Saya jadi bisa merasakan apa rasanya saat nama seseorang, terutama pendapatnya, luas disebut-sebut dalam media. "Oh begini to, rasanya, menjadi bahan pemberitaan?"
Bukan yang menjadi tersangka kejahatan, lho. Tetapi yang menjadi narasumber, yaitu mereka yang perkataannya dianggap mencerahkan --bukan mengeruhkan--, lantas diminta mengomentari beberapa masalah aktual yang sedang mencuat di masyarakat.
Tentunya narasumber begini bukan sembarang orang. Biasanya mereka adalah orang yang -- atau dianggap-- berkompeten pada satu permasalahan yang saat itu dibicarakan. Atas dasar latar belakang dan pegetahuannya, mereka dianggap pantas memberikan pandangan atas sebuah isu. Lantas, apa kualifikasi saya, sampai-sampai ucapan saya dikutip pada isu budaya seperti ini?
 Dijuluki Gareng
Dijuluki Gareng
Kebetulan dulu semasa kuliah, saya aktif di aneka kegiatan. Sebut saja Senat Mahasiswa FISIP Undip, mahasiswa pecinta alam, SAR universitas, hingga teater kampus FISIP Undip: Teater Ortoddok. Walau begitu, dari seabrek kegiatan yang saya ikuti itu, hanya yang terakhir yang sukses mengantarkan saya menjadi ketua.
Dua tahun (2005-2007) lamanya saya menduduki pucuk tertinggi Teater Ortoddok. Kini, walau sudah lengser dari posisi ketua, saya terhitung masih aktif dalam teater yang berdiri pada 16 Juni 1994 ini.
Apa boleh buat, status saya saat ini masih mahasiswa, belum alumni. Belum kelar-kelar juga skripsi saya. Karena itulah, saya masih tak enak hati untuk melepaskan begitu saja teman-teman lain. Lain ceritanya kalau nanti saya sudah wisuda, atau kerja di luar kota.
Bahkan, saking melekatnya saya dengan teater ini, julukan "Gareng" pada nama saya pun bermula di sini. Kisahnya, di masa awal-awal bergabung, saya mengikuti pelatihan teater dasar di Salatiga yang menjadi syarat calon anggota sebelum sah dilantik menjadi anggota.
Di hari terakhir pelatihan, kami, semua calon anggota baru, didaulat mementaskan sebuah naskah unggulan mereka yang berjudul "Memomamimurtad". Kisahnya mengenai pergulatan pemuda yang digusarkan pada pilihan: iman atau sang gadis, pujaan hatinya.
Di salah satu babak, ada adegan ketika beberapa pemuda yang berdandan ala Gareng, Petruk, dan Bagong, menggoda sang gadis. Saya kebagian peran "Gareng".
Ketika melihat saya masuk panggung dengan dandanan ala "Gareng", yang memang acak-acakan karena dirias oleh amatiran, keluarlah celetukan para senior yang ikut menonton: "Ah, lihat itu, si Dityo! Benar-benar 'natural'. Wajahnya pas sekali dengan 'Gareng'."
"Cocok apa? Dandanan tak karuan begini dibilang cocok!"
Di teater yang berciri khas penggunaan alat musik dan busana tradisional Jawa ini, saya kini lebih sering menjadi sutradara atau penulis naskah. Hal ini karena saya termasuk angkatan "tua" dan tinggal menunggu hitungan bulan untuk lulus kuliah.
Namun, kalau jumlah pemain kurang menjelang jadwal persiapan yang singkat, tak jarang saya dengan semangat juang '45 kembali "turun gunung" menjadi aktor.
Naskah-naskah yang kami mainkan seputar kehidupan sosial, karut-marutnya wajah anak muda, hingga satir tentang manusia yang acapkali penuh citra diri palsu, kesombongan, dan lupa diri. Dasar yang kami ambil adalah firman-firman TUHAN.
Teater ini didirikan oleh Lik Agus MerDK dan kawan-kawan. Lik Agus sendiri, kini menjadi sutradara-cum-penulis naskah di lembaga multimedia Christoperus yang bergerak di pembuatan film-film rohani Kristen.
Mimik Serius
Berangkat dari kapasitas ini, teman saya, Brando, sang reporter-lepas Antara, tiba-tiba datang menanyakan pendapat tentang topik yang bertemakan budaya dan sosial. Tak seperti biasanya, wajah kawan asal Pematang Siantar, Medan, yang sudah lama saya kenal sejak di kampus ini, berubah serius.
"Dit, bagaimana pendapat kau tentang pengesahan RUU-Pornografi yang belakangan ini ramai?"
Karena dadakan, dan datang dari teman yang saya kenal suka bergurau, saya pun menjawab ala kadarnya:
LIHAT DETAIL BERITA: UU-Pornografi Intervensi Kebebasan dan Kehidupan Pribadi
Di lain hari, saat sedang asyik bercanda di warung kopi, wajahnya tiba-tiba berubah serius, dan berkata: "Lae (bahasa Batak untuk panggilan teman sebaya), bagaimana pendapat kau tentang film nasional kita saat ini?"
LIHAT DETAIL BERITA: Film Nasional Tak Imbang
Pada 28 Oktober 2008, momentum Sumpah Pemuda, ia pun begitu. Saat main ke indekos saya, tak ada hujan tak ada angin, lagi-lagi dia bertanya dengan mimik serius, persis Bung Karno saat menyerukan Proklamasi: "Lae, kuminta pendapat kau tentang Sumpah Pemuda. Apa kini korelasinya dengan Pancasila?"
LIHAT DETAIL BERITA: Pancasila dan Sumpah Pemuda Mulai Luntur di Jiwa Bangsa
Jujur, di semua kesempatan itu, saya benar-benar menjawab dengan "ala-kadarnya". Maklum, wawancara singkat itu benar-benar tanpa persiapan. Tetapi, meski saya belum pernah sekalipun menulis tentang topik-topik itu, saya memang banyak membaca mengenainya. Jadi, tak bodoh-bodoh amatlah waktu itu.
Ketika itu, Brando memang sudah minta ijin mengutip ucapan saya untuk beritanya (dalam etika pers, ucapan yang dikutip dalam berita tanpa pemberitahuan sebelumnya, bisa dituntut sang narasumber). Namun, karena suasana waktu itu sedang rileks, kami sedang mengobrol penuh gurauan di warung kopi, saya tak mengira ia benar-benar akan ucapannya.
Sebulan setelah pemuatan beritanya, dengan logat Bataknya, Brando baru memberi tahu saya: "Hei Lae! Beritaku yang pakai narasumber kau itu sudah dimuat. Malah di Harian SIB (Medan), dipajang cukup besar."
"Berita yang mana?"
"Ah, masa Lae lupa? Tempo hari, waktu kita nongkrong di warung kopi hari itu!"
Ah, ya sudah, hitung-hitung publikasi diri gratis. Masakan menulis perkataan orang terus. Sekali-sekali menjadi narasumber, tak apalah! Lantas, kalau ditanyakan: enak mana menjadi reporter atau narasumber? Sama saja! Sama-sama susah: pantang menerima amplop!
Enak Mana, Reporter atau Narasumber?
Oleh Anindityo Wicaksono
BELAKANGAN ini nama saya sering disebut-sebut sebagai narasumber dalam beberapa media cetak dan online. Ada tiga permasalahan bertemakan budaya dan sosial yang menyertakan pandangan pribadi saya ini: RUU-Pornografi, film nasional, dan ideologi Pancasila dalam momentum Sumpah Pemuda 2008.
Sebenarnya, berita-berita ini awalnya bersumber dari satu media: Kantor Berita Antara Biro Jateng. Reporternya yang menulis, Brando Sinurat, pun kawan kental saya sendiri. Namun, karena memang jaringan kantor berita ini menasional, jadilah warta yang memuat nama saya itu tersebar luas.
Mulai dari Harian Sinar Indonesia Baru (Medan), Harian Pelita, Harian Suara Karya, Institut Perempuan Online, Gatra Online, hingga menjadi pembahasan dalam beberapa blog yang memuat analisis aneka berita. Lantas apa rasanya melihat nama sendiri masuk media? Kaget bin bangga. Selain itu, lucu.
Kok lucu? Ya, saya yang notabene reporter, jurnalis, yang biasa mewawancarai dan menuliskan pendapat para pakar di surat kabar, kini malah muncul di koran sebagai narasumber. Sombong? Tidak juga. Saya cuma jadi lebih paham. Saya jadi bisa merasakan apa rasanya saat nama seseorang, terutama pendapatnya, luas disebut-sebut dalam media. "Oh begini to, rasanya, menjadi bahan pemberitaan?"
Bukan yang menjadi tersangka kejahatan, lho. Tetapi yang menjadi narasumber, yaitu mereka yang perkataannya dianggap mencerahkan --bukan mengeruhkan--, lantas diminta mengomentari beberapa masalah aktual yang sedang mencuat di masyarakat.
Tentunya narasumber begini bukan sembarang orang. Biasanya mereka adalah orang yang -- atau dianggap-- berkompeten pada satu permasalahan yang saat itu dibicarakan. Atas dasar latar belakang dan pegetahuannya, mereka dianggap pantas memberikan pandangan atas sebuah isu. Lantas, apa kualifikasi saya, sampai-sampai ucapan saya dikutip pada isu budaya seperti ini?
 Dijuluki Gareng
Dijuluki GarengKebetulan dulu semasa kuliah, saya aktif di aneka kegiatan. Sebut saja Senat Mahasiswa FISIP Undip, mahasiswa pecinta alam, SAR universitas, hingga teater kampus FISIP Undip: Teater Ortoddok. Walau begitu, dari seabrek kegiatan yang saya ikuti itu, hanya yang terakhir yang sukses mengantarkan saya menjadi ketua.
Dua tahun (2005-2007) lamanya saya menduduki pucuk tertinggi Teater Ortoddok. Kini, walau sudah lengser dari posisi ketua, saya terhitung masih aktif dalam teater yang berdiri pada 16 Juni 1994 ini.
Apa boleh buat, status saya saat ini masih mahasiswa, belum alumni. Belum kelar-kelar juga skripsi saya. Karena itulah, saya masih tak enak hati untuk melepaskan begitu saja teman-teman lain. Lain ceritanya kalau nanti saya sudah wisuda, atau kerja di luar kota.
Bahkan, saking melekatnya saya dengan teater ini, julukan "Gareng" pada nama saya pun bermula di sini. Kisahnya, di masa awal-awal bergabung, saya mengikuti pelatihan teater dasar di Salatiga yang menjadi syarat calon anggota sebelum sah dilantik menjadi anggota.
Di hari terakhir pelatihan, kami, semua calon anggota baru, didaulat mementaskan sebuah naskah unggulan mereka yang berjudul "Memomamimurtad". Kisahnya mengenai pergulatan pemuda yang digusarkan pada pilihan: iman atau sang gadis, pujaan hatinya.
Di salah satu babak, ada adegan ketika beberapa pemuda yang berdandan ala Gareng, Petruk, dan Bagong, menggoda sang gadis. Saya kebagian peran "Gareng".
Ketika melihat saya masuk panggung dengan dandanan ala "Gareng", yang memang acak-acakan karena dirias oleh amatiran, keluarlah celetukan para senior yang ikut menonton: "Ah, lihat itu, si Dityo! Benar-benar 'natural'. Wajahnya pas sekali dengan 'Gareng'."
"Cocok apa? Dandanan tak karuan begini dibilang cocok!"
Di teater yang berciri khas penggunaan alat musik dan busana tradisional Jawa ini, saya kini lebih sering menjadi sutradara atau penulis naskah. Hal ini karena saya termasuk angkatan "tua" dan tinggal menunggu hitungan bulan untuk lulus kuliah.
Namun, kalau jumlah pemain kurang menjelang jadwal persiapan yang singkat, tak jarang saya dengan semangat juang '45 kembali "turun gunung" menjadi aktor.
Naskah-naskah yang kami mainkan seputar kehidupan sosial, karut-marutnya wajah anak muda, hingga satir tentang manusia yang acapkali penuh citra diri palsu, kesombongan, dan lupa diri. Dasar yang kami ambil adalah firman-firman TUHAN.
Teater ini didirikan oleh Lik Agus MerDK dan kawan-kawan. Lik Agus sendiri, kini menjadi sutradara-cum-penulis naskah di lembaga multimedia Christoperus yang bergerak di pembuatan film-film rohani Kristen.
Mimik Serius
Berangkat dari kapasitas ini, teman saya, Brando, sang reporter-lepas Antara, tiba-tiba datang menanyakan pendapat tentang topik yang bertemakan budaya dan sosial. Tak seperti biasanya, wajah kawan asal Pematang Siantar, Medan, yang sudah lama saya kenal sejak di kampus ini, berubah serius.
"Dit, bagaimana pendapat kau tentang pengesahan RUU-Pornografi yang belakangan ini ramai?"
Karena dadakan, dan datang dari teman yang saya kenal suka bergurau, saya pun menjawab ala kadarnya:
LIHAT DETAIL BERITA: UU-Pornografi Intervensi Kebebasan dan Kehidupan Pribadi
Di lain hari, saat sedang asyik bercanda di warung kopi, wajahnya tiba-tiba berubah serius, dan berkata: "Lae (bahasa Batak untuk panggilan teman sebaya), bagaimana pendapat kau tentang film nasional kita saat ini?"
LIHAT DETAIL BERITA: Film Nasional Tak Imbang
LIHAT DETAIL BERITA: Pancasila dan Sumpah Pemuda Mulai Luntur di Jiwa Bangsa
Jujur, di semua kesempatan itu, saya benar-benar menjawab dengan "ala-kadarnya". Maklum, wawancara singkat itu benar-benar tanpa persiapan. Tetapi, meski saya belum pernah sekalipun menulis tentang topik-topik itu, saya memang banyak membaca mengenainya. Jadi, tak bodoh-bodoh amatlah waktu itu.
Ketika itu, Brando memang sudah minta ijin mengutip ucapan saya untuk beritanya (dalam etika pers, ucapan yang dikutip dalam berita tanpa pemberitahuan sebelumnya, bisa dituntut sang narasumber). Namun, karena suasana waktu itu sedang rileks, kami sedang mengobrol penuh gurauan di warung kopi, saya tak mengira ia benar-benar akan ucapannya.
Sebulan setelah pemuatan beritanya, dengan logat Bataknya, Brando baru memberi tahu saya: "Hei Lae! Beritaku yang pakai narasumber kau itu sudah dimuat. Malah di Harian SIB (Medan), dipajang cukup besar."
"Berita yang mana?"
"Ah, masa Lae lupa? Tempo hari, waktu kita nongkrong di warung kopi hari itu!"
* * *
Ah, ya sudah, hitung-hitung publikasi diri gratis. Masakan menulis perkataan orang terus. Sekali-sekali menjadi narasumber, tak apalah! Lantas, kalau ditanyakan: enak mana menjadi reporter atau narasumber? Sama saja! Sama-sama susah: pantang menerima amplop!






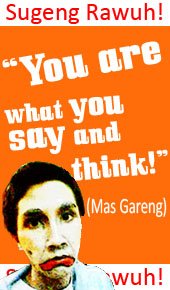



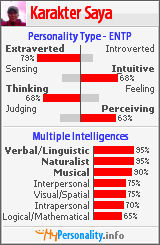









gadis rantau memilih jadi narasumber.hi..hi..ehm..begitu ya caranya liputan. masukan yang menarik banget buat aku nih. mau belajar liputan dan nulis yang baik ah...
BalasHapus