Semarang, 9 November 2008
Beratnya Menjadi Mapala
Oleh Anindityo Wicaksono

JARUM jam baru menunjukkan pukul 02.00. Irama sepatu trek (boot gunung) berderap memecah keheningan di pagi buta itu. Sesosok pria muda, berambut gondrong sebahu, terburu-buru melangkahkan kaki ke sebuah aula berukuran 15 x 15 meter di lantai dua gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Diponegoro, Semarang.
Pakaian lapangan rajutan (flannel) yang dikenakannya terlihat kumal. Matanya sembab. Ia tak tidur semalaman. Sepatu berbahan kulit miliknya diinjakkan masuk ke ruangan yang berisikan 20-an mahasiswa yang sedang terlelap itu.
"Banguunn...! Banguunn...! Dalam 10 hitungan, baris satu saf dengan seragam lengkap!" pekiknya lantang, sejurus kemudian.
Bak berondongan petasan di malam Tahun Baru, suaranya yang memekakkan telinga itu sontak membangunkan puluhan mahasiswa yang sedang tenggelam dalam pesona mimpi. Kocar-kacir mereka dibuatnya. Yang cepat bangkit, lantas menendang-nendang kawannya yang belum juga bangun.
"1... 2... 3...," pemuda gondrong itu melanjutkan hitungan tanpa peduli.
Sejurus kemudian, mereka segera beranjak, kelimpungan mencari aneka perlengkapan yang tercecer ke seantero ruangan: baju flannel, topi rimba, tas carrier, dan sepatu trek.
Hari itu, medio Juni 2004, para mahasiswa ini sedang menjalani pendidikan dasar (diksar) sebagai prosesi menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa (UKM) mahasiswa pecinta alam (Wapeala) Undip, Semarang.
Tak mudah memang, untuk menjadi anggota di UKM itu. Bahkan, boleh dibilang, proses pendidikan yang harus dilakoni hampir setara dengan proses diksar para calon serdadu.
Selain lama, ia menganut sistem seleksi gugur: hanya yang paling akhir bertahan yang lolos. Peserta harus tahan menempa ujian mental dan fisik yang tak sembarangan.
Menurut Aditya (20), Ketua Badan Penerimaan Anggota (BPA) Wapela Undip, keseluruhan tahap dari penerimaan hingga pelantikan calon anggota, total memakan waktu enam bulan. Prosesnya dibagi lima divisi berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, yaitu gunung-hutan, selam, susur gua, arung jeram, dan panjat tebing.
Untuk gunung-hutan, atau yang biasa disebut mountaneering, banyak sekali tehnik yang diajarkan kepada para calon anggota. "Mulai dari keterampilan hidup di alam bebas, navigasi peta, membaca kompas, hingga tehnik survival," bebernya.
Menurut Syaiful (23), Ketua Wapeala Undip, petualangan alam bebas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak hal yang wajib dikuasai seorang pegiat alam bebas jika ingin selamat menggeluti dunia petualangan. Banyak safety-procedure yang harus dipahami.
"Sebelum mengarungi alam yang susah ditebak, kita harus membekali diri dengan persiapan yang matang. Minim persiapan dan perencanaan bisa mengakibatkan kematian," ujar mahasiswa Fakulas Perikanan ini.
Menurut dia, sebelum memutuskan mendaki gunung, ada beberapa keterampilan dasar yang wajib kita ketahui. Hal ini penting untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan dihadapi pendaki, seperti kesasar, kelelahan, atau hipotermia (penyakit di ketinggian).
"Keterampilan ini antara lain tehnik packing yang benar, manajemen perjalanan dan logistik, membuat tenda dengan jas hujan, membaca peta tipografi gunung, hingga tehnik navigasi darat berbasis alat kompas," jelasnya.
Berjalan Kaki
Pada sesi "solo-camp" dalam diksar mountaneering, para calon anggota Wapeala ini dipaksa berani hidup mandiri di tengah belantara rimba. Selama tiga hari, pelatihan yang bertempat di Bumi Perkemahan Penggaron, Ungaran, Kabupaten Semarang, ini menempatkan tenda-tenda mereka saling berjauhan. Hal ini agar para peserta tak dapat berkomunikasi dan mengetahui keberadaan masing-masing.
"Kami tidur hanya beratapkan tenda dari jas hujan dan ditemani tiga batang lilin, senter, dan catatan harian. Jauh dari siapa-siapa," kenang Andi Wahyu (20), salah seorang calon anggota.
Di lain hari, pada sesi "survival", mereka dilatih mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan bahan-bahan makanan alami dari hutan. Selama tiga hari, mereka "dilepas" hidup di belantara rimba kaki Gunung Ungaran. Masing-masing mereka hanya dibekali makanan seadanya: tiga bungkus mie instan, sebatang lilin, seperempat kilogram gula, dan setengah botol air mineral.
"Akibat keterbatasan ini, mau tak mau kami harus berpikir keras dan saling bekerja sama demi menyambung hidup. Persis acara reality-show 'Survival' yang diputar di salah satu stasiun swasta," ujar mahasiswa Fakultas Hukum ini.
Karena berada di tempat yang sama, mereka saling membagi tugas. Para lelaki merambahi hutan "berburu" bahan-bahan makanan dan mengumpulkan kayu bakar. Jenis makanan ini beragam, mulai dari dedaunan, jamur, jantung pisang, tokek, bekicot, hingga cacing terpaksa dijadikan penyambung hidup. Sedangkan para wanitanya, meracik dan memasak.
Untuk alasan kesehatan, sebelumnya mereka diajarkan di kampus bagaimana membedakan jenis makanan yang dapat dimakan dan yang tidak. Pasalnya, tak semua bahan ini aman. Mereka harus pintar-pintar memilah. Salah-salah, fatal akibatnya: mati keracunan.
Pelatihan untuk mountaneering ini digabung dengan susur gua. Setelah sesi "survival" usai, mereka melanjutkan berjalan kaki ke Gua Kiskenda, Kendal, Jawa Tengah, sekitar 20 kilometer dari kaki Ungaran. Delapan jam nonstop mereka berjalan kaki maraton.
 Ekspedisi
Ekspedisi
Seminggu penuh para peserta ini menghabiskan waktu di lapangan untuk melakoni pelatihan dua divisi gabungan ini. Saking lamanya di hutan, tanpa cermin dan alat-alat mandi, para pegiat alam ini pulang dengan kondisi memprihatinkan. Rambut kusam dan badan bau hutan. Baju lusuh tak beraturan.
Divisi sisanya, arung jeram dan panjat tebing, rata-rata menghabiskan waktu tiga hari di lapangan. Arung jeram bertempat di Sungai Elo, Magelang, dan panjat tebing di Tebing Kali Pancur, Salatiga.
Selesaikah? Belum. Di tahap akhir, setelah menyelesaikan lima divisi, para peserta masih harus melakoni ekspedisi sesuai divisi yang diminatinya. Tahap ini amat menentukan apakah seseorang layak mendapatkan nomor anggota atau tidak. Untuk tempat tujuan, mereka yang sudah terbagi dalam tim-tim ini bebas menentukan.
Aditya mengatakan, karena namanya "ekspedisi", masing-masing regu wajib mencari tempat yang belum pernah dikunjungi angkatan-angkatan sebelumnya. Minimal di Pulau Jawa selain Jawa Tengah, seperti Jawa Barat atau Jawa Timur.
"Dalam perjalanan ini, selain membuat laporan dalam bentuk karya tulis dan dokumentasi foto, para calon anggota juga harus membawa misi, seperti pemetaan, studi demografis, atau bersih gunung bagi yang memilih divisi gunung-hutan," terangnya.
Bagi mereka, mungkin benar apa yang dikatakan Lord Byron, pujangga masyhur Inggris, dalam syairnya ini: There is a pleasure in the pathless woods/ There is a rapture on the lonely shore/ There is society, where none intrudes/ By the deep sea, and music in its roar: I love not man the less, but Nature more.
(Ada kesenangan dalam hutan tanpa jalan setapak/ Ada kegembiraan pada pantai yang sunyi/ Ada masyarakat yang tidak memunyai pengacau/
Ada alunan musik dari samudera dalam: Saya mencintai manusia, tapi lebih suka kepada alam)
Beratnya Menjadi Mapala
Oleh Anindityo Wicaksono

JARUM jam baru menunjukkan pukul 02.00. Irama sepatu trek (boot gunung) berderap memecah keheningan di pagi buta itu. Sesosok pria muda, berambut gondrong sebahu, terburu-buru melangkahkan kaki ke sebuah aula berukuran 15 x 15 meter di lantai dua gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Diponegoro, Semarang.
Pakaian lapangan rajutan (flannel) yang dikenakannya terlihat kumal. Matanya sembab. Ia tak tidur semalaman. Sepatu berbahan kulit miliknya diinjakkan masuk ke ruangan yang berisikan 20-an mahasiswa yang sedang terlelap itu.
"Banguunn...! Banguunn...! Dalam 10 hitungan, baris satu saf dengan seragam lengkap!" pekiknya lantang, sejurus kemudian.
Bak berondongan petasan di malam Tahun Baru, suaranya yang memekakkan telinga itu sontak membangunkan puluhan mahasiswa yang sedang tenggelam dalam pesona mimpi. Kocar-kacir mereka dibuatnya. Yang cepat bangkit, lantas menendang-nendang kawannya yang belum juga bangun.
"1... 2... 3...," pemuda gondrong itu melanjutkan hitungan tanpa peduli.
Sejurus kemudian, mereka segera beranjak, kelimpungan mencari aneka perlengkapan yang tercecer ke seantero ruangan: baju flannel, topi rimba, tas carrier, dan sepatu trek.
Hari itu, medio Juni 2004, para mahasiswa ini sedang menjalani pendidikan dasar (diksar) sebagai prosesi menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa (UKM) mahasiswa pecinta alam (Wapeala) Undip, Semarang.
Tak mudah memang, untuk menjadi anggota di UKM itu. Bahkan, boleh dibilang, proses pendidikan yang harus dilakoni hampir setara dengan proses diksar para calon serdadu.
Selain lama, ia menganut sistem seleksi gugur: hanya yang paling akhir bertahan yang lolos. Peserta harus tahan menempa ujian mental dan fisik yang tak sembarangan.
Menurut Aditya (20), Ketua Badan Penerimaan Anggota (BPA) Wapela Undip, keseluruhan tahap dari penerimaan hingga pelantikan calon anggota, total memakan waktu enam bulan. Prosesnya dibagi lima divisi berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, yaitu gunung-hutan, selam, susur gua, arung jeram, dan panjat tebing.
Untuk gunung-hutan, atau yang biasa disebut mountaneering, banyak sekali tehnik yang diajarkan kepada para calon anggota. "Mulai dari keterampilan hidup di alam bebas, navigasi peta, membaca kompas, hingga tehnik survival," bebernya.
Menurut Syaiful (23), Ketua Wapeala Undip, petualangan alam bebas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak hal yang wajib dikuasai seorang pegiat alam bebas jika ingin selamat menggeluti dunia petualangan. Banyak safety-procedure yang harus dipahami.
"Sebelum mengarungi alam yang susah ditebak, kita harus membekali diri dengan persiapan yang matang. Minim persiapan dan perencanaan bisa mengakibatkan kematian," ujar mahasiswa Fakulas Perikanan ini.
Menurut dia, sebelum memutuskan mendaki gunung, ada beberapa keterampilan dasar yang wajib kita ketahui. Hal ini penting untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan dihadapi pendaki, seperti kesasar, kelelahan, atau hipotermia (penyakit di ketinggian).
"Keterampilan ini antara lain tehnik packing yang benar, manajemen perjalanan dan logistik, membuat tenda dengan jas hujan, membaca peta tipografi gunung, hingga tehnik navigasi darat berbasis alat kompas," jelasnya.
Berjalan Kaki
Pada sesi "solo-camp" dalam diksar mountaneering, para calon anggota Wapeala ini dipaksa berani hidup mandiri di tengah belantara rimba. Selama tiga hari, pelatihan yang bertempat di Bumi Perkemahan Penggaron, Ungaran, Kabupaten Semarang, ini menempatkan tenda-tenda mereka saling berjauhan. Hal ini agar para peserta tak dapat berkomunikasi dan mengetahui keberadaan masing-masing.
"Kami tidur hanya beratapkan tenda dari jas hujan dan ditemani tiga batang lilin, senter, dan catatan harian. Jauh dari siapa-siapa," kenang Andi Wahyu (20), salah seorang calon anggota.
Di lain hari, pada sesi "survival", mereka dilatih mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan bahan-bahan makanan alami dari hutan. Selama tiga hari, mereka "dilepas" hidup di belantara rimba kaki Gunung Ungaran. Masing-masing mereka hanya dibekali makanan seadanya: tiga bungkus mie instan, sebatang lilin, seperempat kilogram gula, dan setengah botol air mineral.
"Akibat keterbatasan ini, mau tak mau kami harus berpikir keras dan saling bekerja sama demi menyambung hidup. Persis acara reality-show 'Survival' yang diputar di salah satu stasiun swasta," ujar mahasiswa Fakultas Hukum ini.
Karena berada di tempat yang sama, mereka saling membagi tugas. Para lelaki merambahi hutan "berburu" bahan-bahan makanan dan mengumpulkan kayu bakar. Jenis makanan ini beragam, mulai dari dedaunan, jamur, jantung pisang, tokek, bekicot, hingga cacing terpaksa dijadikan penyambung hidup. Sedangkan para wanitanya, meracik dan memasak.
Untuk alasan kesehatan, sebelumnya mereka diajarkan di kampus bagaimana membedakan jenis makanan yang dapat dimakan dan yang tidak. Pasalnya, tak semua bahan ini aman. Mereka harus pintar-pintar memilah. Salah-salah, fatal akibatnya: mati keracunan.
Pelatihan untuk mountaneering ini digabung dengan susur gua. Setelah sesi "survival" usai, mereka melanjutkan berjalan kaki ke Gua Kiskenda, Kendal, Jawa Tengah, sekitar 20 kilometer dari kaki Ungaran. Delapan jam nonstop mereka berjalan kaki maraton.
 Ekspedisi
EkspedisiSeminggu penuh para peserta ini menghabiskan waktu di lapangan untuk melakoni pelatihan dua divisi gabungan ini. Saking lamanya di hutan, tanpa cermin dan alat-alat mandi, para pegiat alam ini pulang dengan kondisi memprihatinkan. Rambut kusam dan badan bau hutan. Baju lusuh tak beraturan.
Divisi sisanya, arung jeram dan panjat tebing, rata-rata menghabiskan waktu tiga hari di lapangan. Arung jeram bertempat di Sungai Elo, Magelang, dan panjat tebing di Tebing Kali Pancur, Salatiga.
Selesaikah? Belum. Di tahap akhir, setelah menyelesaikan lima divisi, para peserta masih harus melakoni ekspedisi sesuai divisi yang diminatinya. Tahap ini amat menentukan apakah seseorang layak mendapatkan nomor anggota atau tidak. Untuk tempat tujuan, mereka yang sudah terbagi dalam tim-tim ini bebas menentukan.
Aditya mengatakan, karena namanya "ekspedisi", masing-masing regu wajib mencari tempat yang belum pernah dikunjungi angkatan-angkatan sebelumnya. Minimal di Pulau Jawa selain Jawa Tengah, seperti Jawa Barat atau Jawa Timur.
"Dalam perjalanan ini, selain membuat laporan dalam bentuk karya tulis dan dokumentasi foto, para calon anggota juga harus membawa misi, seperti pemetaan, studi demografis, atau bersih gunung bagi yang memilih divisi gunung-hutan," terangnya.
Bagi mereka, mungkin benar apa yang dikatakan Lord Byron, pujangga masyhur Inggris, dalam syairnya ini: There is a pleasure in the pathless woods/ There is a rapture on the lonely shore/ There is society, where none intrudes/ By the deep sea, and music in its roar: I love not man the less, but Nature more.
(Ada kesenangan dalam hutan tanpa jalan setapak/ Ada kegembiraan pada pantai yang sunyi/ Ada masyarakat yang tidak memunyai pengacau/
Ada alunan musik dari samudera dalam: Saya mencintai manusia, tapi lebih suka kepada alam)





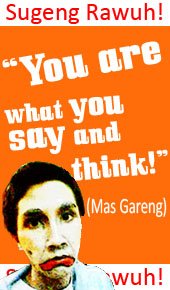



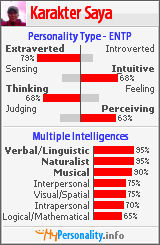









Wah asyik sekali cerita tentang Mapala. Mapala mendidik kita agar mencintai alam dan lingkungan. Belajar mandiri, tidak cengeng, melatih daya juang, tidak mudah menyerah. Selalu yakin bahwa bagaimanapun caranya, ada jalan untuk mencapai puncak. Salam.
BalasHapus