Semarang, 2 Mei 2009
Labirin Pendidikan Nasional
Oleh Anindityo Wicaksono
PELAKSANAAN ujian nasional (UN) di setiap penghujung tahun ajaran memang tak pernah sepi polemik. Hampir seluruh pihak yang terlibat, mulai dari siswa, orang tua siswa, hingga pakar dan pemerhati pendidikan, kukuh menolak dengan beragam pertimbangan empiris. Namun pemerintah tetap bergeming; keras hati bahwa UN merupakan harga mati dalam mengukur mutu pendidikan nasional.
Kemantapan pemerintah pada hajat akbar tahunan ini terlihat dari alokasi biaya dan energi yang tak main-main. Tak tanggung-tanggung dana yang disediakan: tidak kurang dari Rp439 miliar. Pengawas yang ambil bagian mencapai tidak kurang satu juta orang (Kompas, 17/4).
Pemerintah juga terus menaikkan standarnya demi meningkatkan kualitas luaran yang diharapkannya. Nilai kelulusan UN 2009 dinaikkan dari 5,00 menjadi 5,25. Jumlah mata pelajaran yang diujikan untuk SMP-SMA ditambah dari 3 menjadi 6 mata pelajaran.
Konsekuensinya, siswa, yang traumatis dengan UN 2008 yang banyak “menelan korban”, tak punya pilihan lain: ikut “berperang” atau mundur yang berarti kehilangan masa tiga tahun begitu saja.
Walau begitu, UN sebagai pemicu perbaikan dan alat pemetaan mutu pendidikan nyatanya belum berbicara banyak. Saban pelaksanannya, selalu saja ditemukan aneka kasus kecurangan sistematis yang justru kian mengeruhkan keadaan.
Betapa tidak, para pelakunya justru datang dari pihak intern sekolah: kepala sekolah, guru, tim sukses sekolah, bahkan dinas pendidikan (Wawasan, 28/4). Adapun kasus terbanyak ialah bocoran soal dan jawaban, lembar jawaban palsu, kasus pembetulan jawaban oleh guru, hingga penipuan jual-beli soal dan lembar jawaban.
Lantas, siapa biang keroknya? Pemerintah sebagai “subyek” pembuat kebijakan, ataukah para siswa dan sekolah sebagai “obyek” yang mencari jalan keluar lantas menghalalkan segala cara demi menuruti kemauan “subyek”?
Hakim penentu
Tak dimungkiri, serbakecurangan yang ditemukan menunjukkan, tataran konsep yang bergelimang hal-hal ideal ternyata tak selamanya sejalan dengan pelaksanaan, dan, terutama, pengawasannya. Ini adalah buah logis pragmatisme yang dibawa UN. Bahwa hasil ujian berdurasi dua jam dijadikan pengukur keberhasilan proses pembelajaran tiga tahun, memang sarat intrik dan kecurangan.
Premis dari potret hitam pelaksanaan UN jelas. Terjadi sebuah pergeseran paradigma dalam memaknai nilai. Ia tereduksi sedemikian rupa dan tak pernah sama lagi sejak UN diterapkan. Nilai, dari sekadar bahan evaluasi kekurangan-kelebihan, baik bagi siswa maupun pengajar, berubah menjadi momok tunggal penentu masa depan siswa.
Inilah yang diwanti-wanti pedagog senior Mochtar Buchori (1995): “Jika kita kian terjebak hiruk-pikuk aneka persoalan ‘hilir’, aneka pemikiran dasar yang memberi arah kebijakan dan praktik pendidikan nasional akan terabaikan.” Walau begitu, terjadinya aneka praktik kecurangan yang melibatkan pihak intern sekolah tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada mereka.
Jika dirunut ke belakang, munculnya UN sejak 2003 berawal dari keinginan pemerintah men-standarisasi mutu sistem pendidikan nasional. Karena UN dianggap mampu mendongkrak kualitas kelulusan siswa, standarnya ditingkatkan secara periodik hingga mencapai besaran akhir yang diharapkan.
Jelas, UN ialah buah kekurangpahaman pemerintah terhadap realitas pendidikan nasional. Tersebar menjadi 33 provinsi, Indonesia memiliki sejuta keanekaragaman dan latar belakang ekonomi-sosial-budaya-budaya.
Nilai 5,25 bisa jadi ringan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Namun tak adil rasanya jika standar “kota” ini diterapkan pula di pelosok Provinsi Belitung, misalnya, desa setting sentral novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, di mana akses siswa terhadap pengetahuan amat terbatas.
Benarlah setiap sekolah mensyaratkan proses evaluasi tahap akhir berupa ujian. Namun jangan lupa bahwa tidak selamanya evaluasi begitu saja berhak menentukan kelulusan akhir. Apalagi jika predikat tidak lulus mengharuskan peserta didik mengulangi proses pembelajaran satu tahun kemudian untuk dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Bagi yang tidak lulus, pemerintah memang menyodorkan ijasah penyetaraan (Program Paket A/B/C). Namun, hemat penulis, langkah ini hanyalah solusi pragmatis dan reaktif yang dipicu kebingungan sang penyelenggara.
Nyatanya tidak semua perguruan tinggi menerima siswa berijasah Paket C (bagi siswa SMA). Pun penulis yakin, sangat berat rasanya siswa yang telah mennempuh pendidikan selama tiga tahun penuh menerima ijasah dengan "kasta” yang lebih rendah hanya gara-gara kegagalan ujian tiga hari.
Labirin
Amanat pendidikan sesuai UUD 1945 pasal 31 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.
Adapun menurut UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keamanan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan.
Sesuai konstitusi, tujuan utama pendidikan, selain peningkatan kecerdasan-keterampilan, juga aspek-aspek moral-spiritual. Yang terakhir bahkan disebutkan lebih dulu.
Jika demikian, maraknya aksi curang tersistematis, yang bahkan digawangi oknum sekolah, menujukkan, pendidikan telah gagal; melenceng jauh dari cita-cita awalnya. Pendidikan kian mendewakan pencapaian nilai namun makin miskin empati.
Saatnya pendidikan nasional keluar dari kotak labirinnya. Ketika problematika UN menjadi tali tak berpangkal, solusi jangka panjang harus berpatut diri pada konstitusi. Pendidikan, mengutip bapak pedagogi Paulo Freire, harus kembali pada fungsinya semula: memerdekakan. Kita kembali pada semangat awal yang kini kita namai ESQ (emotional-spiritual quotient), kecerdasan spiritual-emosional. (*)
(Dimuat di Koran Sore Wawasan, 5 April 2009)
Labirin Pendidikan Nasional
Oleh Anindityo Wicaksono
Kemantapan pemerintah pada hajat akbar tahunan ini terlihat dari alokasi biaya dan energi yang tak main-main. Tak tanggung-tanggung dana yang disediakan: tidak kurang dari Rp439 miliar. Pengawas yang ambil bagian mencapai tidak kurang satu juta orang (Kompas, 17/4).
Pemerintah juga terus menaikkan standarnya demi meningkatkan kualitas luaran yang diharapkannya. Nilai kelulusan UN 2009 dinaikkan dari 5,00 menjadi 5,25. Jumlah mata pelajaran yang diujikan untuk SMP-SMA ditambah dari 3 menjadi 6 mata pelajaran.
Konsekuensinya, siswa, yang traumatis dengan UN 2008 yang banyak “menelan korban”, tak punya pilihan lain: ikut “berperang” atau mundur yang berarti kehilangan masa tiga tahun begitu saja.
Walau begitu, UN sebagai pemicu perbaikan dan alat pemetaan mutu pendidikan nyatanya belum berbicara banyak. Saban pelaksanannya, selalu saja ditemukan aneka kasus kecurangan sistematis yang justru kian mengeruhkan keadaan.
Betapa tidak, para pelakunya justru datang dari pihak intern sekolah: kepala sekolah, guru, tim sukses sekolah, bahkan dinas pendidikan (Wawasan, 28/4). Adapun kasus terbanyak ialah bocoran soal dan jawaban, lembar jawaban palsu, kasus pembetulan jawaban oleh guru, hingga penipuan jual-beli soal dan lembar jawaban.
Lantas, siapa biang keroknya? Pemerintah sebagai “subyek” pembuat kebijakan, ataukah para siswa dan sekolah sebagai “obyek” yang mencari jalan keluar lantas menghalalkan segala cara demi menuruti kemauan “subyek”?
Hakim penentu
Tak dimungkiri, serbakecurangan yang ditemukan menunjukkan, tataran konsep yang bergelimang hal-hal ideal ternyata tak selamanya sejalan dengan pelaksanaan, dan, terutama, pengawasannya. Ini adalah buah logis pragmatisme yang dibawa UN. Bahwa hasil ujian berdurasi dua jam dijadikan pengukur keberhasilan proses pembelajaran tiga tahun, memang sarat intrik dan kecurangan.
Premis dari potret hitam pelaksanaan UN jelas. Terjadi sebuah pergeseran paradigma dalam memaknai nilai. Ia tereduksi sedemikian rupa dan tak pernah sama lagi sejak UN diterapkan. Nilai, dari sekadar bahan evaluasi kekurangan-kelebihan, baik bagi siswa maupun pengajar, berubah menjadi momok tunggal penentu masa depan siswa.
Inilah yang diwanti-wanti pedagog senior Mochtar Buchori (1995): “Jika kita kian terjebak hiruk-pikuk aneka persoalan ‘hilir’, aneka pemikiran dasar yang memberi arah kebijakan dan praktik pendidikan nasional akan terabaikan.” Walau begitu, terjadinya aneka praktik kecurangan yang melibatkan pihak intern sekolah tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada mereka.
Jika dirunut ke belakang, munculnya UN sejak 2003 berawal dari keinginan pemerintah men-standarisasi mutu sistem pendidikan nasional. Karena UN dianggap mampu mendongkrak kualitas kelulusan siswa, standarnya ditingkatkan secara periodik hingga mencapai besaran akhir yang diharapkan.
Jelas, UN ialah buah kekurangpahaman pemerintah terhadap realitas pendidikan nasional. Tersebar menjadi 33 provinsi, Indonesia memiliki sejuta keanekaragaman dan latar belakang ekonomi-sosial-budaya-budaya.
Nilai 5,25 bisa jadi ringan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Namun tak adil rasanya jika standar “kota” ini diterapkan pula di pelosok Provinsi Belitung, misalnya, desa setting sentral novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, di mana akses siswa terhadap pengetahuan amat terbatas.
Benarlah setiap sekolah mensyaratkan proses evaluasi tahap akhir berupa ujian. Namun jangan lupa bahwa tidak selamanya evaluasi begitu saja berhak menentukan kelulusan akhir. Apalagi jika predikat tidak lulus mengharuskan peserta didik mengulangi proses pembelajaran satu tahun kemudian untuk dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Bagi yang tidak lulus, pemerintah memang menyodorkan ijasah penyetaraan (Program Paket A/B/C). Namun, hemat penulis, langkah ini hanyalah solusi pragmatis dan reaktif yang dipicu kebingungan sang penyelenggara.
Nyatanya tidak semua perguruan tinggi menerima siswa berijasah Paket C (bagi siswa SMA). Pun penulis yakin, sangat berat rasanya siswa yang telah mennempuh pendidikan selama tiga tahun penuh menerima ijasah dengan "kasta” yang lebih rendah hanya gara-gara kegagalan ujian tiga hari.
Labirin
Amanat pendidikan sesuai UUD 1945 pasal 31 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia.
Adapun menurut UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual keamanan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan.
Sesuai konstitusi, tujuan utama pendidikan, selain peningkatan kecerdasan-keterampilan, juga aspek-aspek moral-spiritual. Yang terakhir bahkan disebutkan lebih dulu.
Jika demikian, maraknya aksi curang tersistematis, yang bahkan digawangi oknum sekolah, menujukkan, pendidikan telah gagal; melenceng jauh dari cita-cita awalnya. Pendidikan kian mendewakan pencapaian nilai namun makin miskin empati.
Saatnya pendidikan nasional keluar dari kotak labirinnya. Ketika problematika UN menjadi tali tak berpangkal, solusi jangka panjang harus berpatut diri pada konstitusi. Pendidikan, mengutip bapak pedagogi Paulo Freire, harus kembali pada fungsinya semula: memerdekakan. Kita kembali pada semangat awal yang kini kita namai ESQ (emotional-spiritual quotient), kecerdasan spiritual-emosional. (*)
(Dimuat di Koran Sore Wawasan, 5 April 2009)






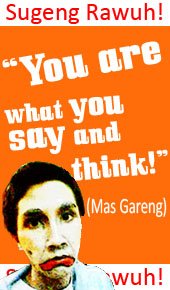



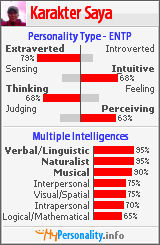









0 komentar:
Posting Komentar