Semarang, 22 Mei 2009
Kunci Keberhasilan SOLOPOS (2)
Oleh Anindityo Wicaksono (penyunting)
NTOK Pancowarno, salah seorang saksi sejarah penerbitan pers di Kota Solo sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an menyatakan pers yang pernah terbit di Solo akhirnya terkubur lebih banyak diakibatkan kurang profesionalnya organisasi industri itu secara keseluruhan (Mulyanto Utomo, 2007: 97).
“Solo punya julukan kuburan koran, itu karena koran yang ditangani waktu itu tidak ada yang profesional. Sebenarnya ada beberapa penulis (wartawan) yang potensial waktu itu, seperti Pak Nur Sahid, Pak Anjar Any dan Pak Sakdani. Mereka itu sudah boleh dikatakan bertaraf nasional. Tapi dalam pengelolaannya tidak ada rambu-rambu yang dibuat pimpinan secara jelas, jadinya ya macet," katanya.
Kalau misalnya waktu itu pemimpin membuat kebijakan merekrut orang yang mampu dan dibayar secara layak, mungkin beda sejarahnya. Beberapa ide pernah Ntok lontarkan, tapi tidak pernah digubris pimpinan, walaupun benar atau salahnya ide itu belum diuji. Misalnya soal mekanisme perekrutan tenaga, menurut dia itu penting sekali.
"Ngapain sih kita digaji segitu (tak cukup layak)? Waktu itu dua ratus ribu. Sebelumnya bahkan kita digaji enam puluh ribu. Ngapain kita digaji sementara tidak ada prospek. Mbok sudah aku nggak usah digaji, gajiku kuwi dikumpulke kanca-kanca untuk merekrut orang yang mampu. Kontrak satu tahun misalkan. Aku malah dikira sok pahlawan.” ujar Ntok.
Sakdani Darmopamudjo mengatakan tahun 1982 Darma Nyata dibuat menjadi bahasa Indonesia. Karena juga sebagian tidak profesional, dalam artian teman-teman (yang bekerja) itu masih merangkap, misalnya merangkap jadi guru dan sebagainya. Yang full ada tapi tidak banyak, terutama penentu-penentu policy orangnya merangkap. Sebenarnya pada tahun itu juga berjalan tapi juga rugi.
Sakdani menuturkan bahwa dia aktif di koran mulai 1965-1966. Sebelumnya dia adalah penulis lepas, pengarang di berbagai majalah, surat kabar. Pertama masuk di Mingguan Andika di Mesen. Pengusahanya namanya Masi Sen seorang Tionghoa, dia juga pengusaha toko emas. Sakdani membuka rubrik Pisungsung berbahasa Jawa. Kemudian Andika pecah menjadi Andika lalu Andika Baru. Sakdani juga mengaku pernah di Mingguan Gelora Berdikari yang terbit bersama Andika tahun 1965-1967.
Gelora Berdikari dulu milik PNI. Pecahnya Andika dan Andika Baru karena manajemennya tidak rukun dan aturan-aturannya tidak kuat. Lalu ada Gelora Berdikari yang tetap terbit, tetapi kemudian tahun 1969 karena ada pemikiran masyarakat terutama masyarakat pecinta bahasa Jawa perlu ada koran berbahasa Jawa. Kemudian lahirlah yang namanya Darmo Kondo.
“Kebetulan saya yang menjadi Pemimpin Redaksi. Tapi itu dilakukan karena adanya kesimpulan, keputusan Musyawarah Kerja Pengarang Sastra Jawa. Yang keputusannya adalah mendirikan koran di Yogya dan Solo. Akhirnya saya kembangkan menjadi Darmo Kondo. Modalnya dari beberapa, tidak hanya dari satu orang tetapi juga dari yayasan. Begitu lahir lalu besar sekali, jumlahnya sampai 33 ribu. Tapi tidak langgeng karena pecah lagi.
Saya (Sakdani) sebagai Pemimpin Redaksi, Pak Tukijo sebagai pemimpin umum tidak cocok dengan manajemen. Unsur-unsurnya ya unsur kurang transparan. Pemimpin Redaksi usianya masih muda yaitu usia 28 tahun. Lalu terjadilah konflik yang akhirnya pecah. Darmo Kondo sendiri saya membuat Darma Nyata. Pemimpin Redaksi nya diganti Pak Maryono yang waktu itu Ketua PWI. Karena dananya lebih, Darma Nyata dapat berkembang sejak tahun 1970 berkembang sampai tahun 1982.”
Dalam perjalanannya hingga mencapai sepuluh tahun, manajemen Harian SOLOPOS oleh informan yang diwawancarai dinilai telah dikelola sebagai mana layaknya sebuah organisasi industri modern.
Sakdani mengatakan, “Yang dimaksud ‘hidup’-nya sebuah media massa itu kan ada hidup yang dalam tanda petik dan juga hidup sesungguhnya. Mingguan Adil itu misalnya, juga Darma Nyata meskipun mampu 28 tahun hidup, tapi hidupnya ya... (seadanya).
Saya (ketika mengelola pers) dikenal teman-teman agak mendingan dalam memberi kesejahteraan. Ada perusahaan pers yang gajinya hanya bisa buat beli es saja. Nah itu pengertian hidup itu kan harus sehat dalam artian yang sebetulnya, karyawan harus sejahtera. Solo bertahun-tahun begitu, karena lahirnya pers di Solo ada ambisi dari orang pers di Solo. SOLOPOS itu menurut saya campuran dari keberhasilan yaitu momennya pas, manajemennya yang lebih baik.
Organisasi yang mengelola pers memang harus seimbang. Kalau kita hanya fokus idealisme, nanti apa yang dipakai buat makan karyawan? Kasarannya kan begitu. Nah sekarang kan banyak teman-teman yang tidak mengindahkan idealisme tadi. Jadi ibarat orang berumah tangga, bukan rasa cinta, kasih sayangnya, tapi seksnya saja. Itu kan harus dipadukan. SOLOPOS sudah melakukan itu.” (Mulyanto Utomo, 2007: 98-99).
Modal usaha
Budaya korporasi profesional yang terbentuk di SOLOPOS bukan terbangun secara serta merta namun melalui proses panjang karena pengaruh komitmen kuat para pendiri lebih khusus lagi para pimpinan. Pengaruh kepemimpinan yang tegas, tanpa kompromi ketika ada pelanggaran telah membentuk budaya disiplin, etos kerja rasa tanggung jawab di tingkat korporasi.
Ketegasan dalam meneggakkan aturan tanpa kompromi ini yang kemudian menimbulkan kepercayaan dari publik. Hal ini pula yang membedakan SOLOPOS dengan koran lain. Budaya kerja seperti ini yang perlu diteruskan dari generasi awal koran ini hingga saat ini dan ke depan. Budaya kerja tersebut salah faktor yang membuat SOLOPOS tetap eksis meski menghadapi para pesaing-pesaingnya.
Seorang akuntan publik di Solo, Rachmad Wahyudi, juga menyebut pengaruh kepemimpinan telah membangun budaya perusahaan dan etos kerja karyawan secara profesional.
“Saya bukan mengagung-agungkan atau melebih-lebihkan seorang Pak Danie (Danie H Soe’oed, Pemred) atau Pak Natur (Bambang Natur Rahadi, Pemimpin Perusahaan), tapi apa yang sudah mereka lakukan itu patut diteladani dan secara jujur harus kita akui eksistensinya," ujar Rachmad.
Mengutip wawancara Harian Kompas dengan Pimred Majalah Berita Mingguan Tempo Goenawan Muhamad yang menyatakan bahwa pers di Indonesia telah berkembang ke arah suatu bisnis, Jakob Oetama berpendapat bahwa pers Indonesia memang telah memasuki fase baru yang dalam pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan postur pers masa lalu.
Pers dulu, tambahnya, umumnya hanya terdiri dari redaksi yang hanya menguasai proses produksi berita; mesin cetak milik orang lain, iklan tidak banyak, oplah juga terbatas. Pers sekarang menjadi lembaga yang lengkap; redaksi, percetakan, manajemen (modern). Ada iklan cukup banyak pencapaian oplah di atas 100.000. Penampilan koran dan majalah itu pun modern, bertata warna dan memberikan kesan ditangani secara profesional (Jacob Oetama, 2001: 303).
Berkaca dari Harian Kompas, seperti dipaparkan Jakob Oetama selaku perintis penerbitan koran nomor satu di Indonesia yang terbit mulai 28 Juni 1965 itu, pada awalnya juga dibangun dalam suatu keterbatasan bahkan kesulitan dalam semua bidang, mulai personalia dalam bidang redaksi hingga personalia bidang distribusi.
“Tetapi kesulitan terbesar pada waktu itu adalah percetakan sehingga harus berpindah-pindah. Perubahan politik besar pada tahun 1965 telah membuat distribusi Kompas bisa ditangani sendiri. Tahun 1972 kami memiliki mesin percetakan sendiri berkat tersedianya kredit modal dari bank pemerintah asal sanggup menyediakan sisanya.
Embrio sikap profesionalisme dalam redaksi maupun dalam pengelolaan bisnis berupa sirkulasi, iklan serta pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting tumbuhnya Kompas sejak itu,” terang Jacoeb.
Hal tersebut berarti pula bahwa modal usaha menjadi hal yang sangat penting dalam penerbitan pers modern yang menekankan profesionalisme sebagai landasan usaha. Begitu pula dengan SOLOPOS saat pertama kali dibangun, untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh para dewan pendiri bahwa penerbitan SOLOPOS harus dilaksanakan secara profesional maka perlu dukungan dana yang memadai.
Profesionalisme
Bambang Natur Rahadi selaku Pemimpin Perusahaan Harian SOLOPOS kala itu menyebut bahwa pemodal, dalam hal ini PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit Harian Bisnis Indonesia) memiliki komitmen untuk menerbitkan koran daerah di Solo ini. Artinya, segala kebutuhan finansial yang berkait dengan sumber daya manusia maupun infrastruktur semaksimal mungkin akan dipenuhi.
Dana yang disediakan untuk SOLOPOS waktu itu awalnya no limit (tidak ada batas). Dalam proyeksi anggaran dari bagian keuangan itu sudah dibuat perkiraan dana selama lima tahun. Dan diproyeksikan dalam tempo lima tahun itu SOLOPOS diproyeksi baru untung. Namun karena proyek SOLOPOS berbarengan dengan krisis ekonomi, maka itu menjadi persoalan tersendiri.
Meski awalnya dana untuk SOLOPOS tidak terbatas, kenyataannya setelah jalan bulan ke-7 sudah tidak ada lagi bahasa no limit karena pada saat-saat seperti itu uang sudah menjadi persoalan termasuk di Bisnis Indonesia selaku induk perusahaan SOLOPOS.
“Kalau mau jujur sebetulnya di bulan-bulan ke-6 setelah terbit itu kami sudah mulai kesulitan karena di Jakarta (Bisnis Indonesia) sendiri sudah ribut. Sampai tahun pertama waktu mulai Maret masuk sampai bulan Maret tahun 1998 saya kira sudah lebih dari Rp3 miliar habis. Dan uang Rp3 miliar waktu itu sudah sangat besar,” ungkap Bambang Natur.
Modal menjadi komponen penting dalam industri pers, karena menurut Jakob Oetama realitas yang berkembang dalam sejarah pers di seluruh dunia memang ke arah profesionalisme seperti itu. Jika pers tidak dapat membiayai dirinya dari penghasilan langganan dan iklan –atau dengan kata lain dari usahanya sendiri—maka pers itu harus memperoleh subsidi dari pihak lain; pemerintah, organisasi politik, atau organisasi kepentingan.
Dalam situasi demikian pers akan terhambat perkembangan profesionalisme dan kebebasannya. Pers yang dalam posisi demikian justru tidak akan dapat menjalankan fungsi “kerohaniannya” atau –yang oleh masyarakat pers kita sering disebut—peranan idealnya (Jacob Oetama, 2001: 307).
Presiden Komisaris Kelompok Kompas Gramedia itu berpendapat, pers tidak dibagi-bagikan secara gratis. Surat kabar yang digratiskan akan kehilangan minat pembacanya, karena dianggap kurang bobot kredibilitasnya. Surat kabar dijual, kecuali untuk memenuhi porsi kredibilitasnya, juga karena proses produksinya memerlukan biaya.
Itu berarti bahwa pers sebagai industri harus memperoleh keuntungan yang berfungsi sebagai komponen untuk keberlangsungan hidup surat kabar itu sendiri; sebab jika hanya impas—sementara ongkos-ongkos produksinya cenderung naik—tidaklah mungkin surat kabar itu mempertahankan kehadirannya.
Surat kabar yang dapat hidup dari penghasilannya sendiri akan lebih dapat menjalankan tanggung jawab idealnya dan memelihara kebebasan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara memadai (Jacob Oetama, 2001: 308).
Bersambung.... (*)
Kunci Keberhasilan SOLOPOS (2)
Oleh Anindityo Wicaksono (penyunting)
NTOK Pancowarno, salah seorang saksi sejarah penerbitan pers di Kota Solo sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an menyatakan pers yang pernah terbit di Solo akhirnya terkubur lebih banyak diakibatkan kurang profesionalnya organisasi industri itu secara keseluruhan (Mulyanto Utomo, 2007: 97).
“Solo punya julukan kuburan koran, itu karena koran yang ditangani waktu itu tidak ada yang profesional. Sebenarnya ada beberapa penulis (wartawan) yang potensial waktu itu, seperti Pak Nur Sahid, Pak Anjar Any dan Pak Sakdani. Mereka itu sudah boleh dikatakan bertaraf nasional. Tapi dalam pengelolaannya tidak ada rambu-rambu yang dibuat pimpinan secara jelas, jadinya ya macet," katanya.
Kalau misalnya waktu itu pemimpin membuat kebijakan merekrut orang yang mampu dan dibayar secara layak, mungkin beda sejarahnya. Beberapa ide pernah Ntok lontarkan, tapi tidak pernah digubris pimpinan, walaupun benar atau salahnya ide itu belum diuji. Misalnya soal mekanisme perekrutan tenaga, menurut dia itu penting sekali.
"Ngapain sih kita digaji segitu (tak cukup layak)? Waktu itu dua ratus ribu. Sebelumnya bahkan kita digaji enam puluh ribu. Ngapain kita digaji sementara tidak ada prospek. Mbok sudah aku nggak usah digaji, gajiku kuwi dikumpulke kanca-kanca untuk merekrut orang yang mampu. Kontrak satu tahun misalkan. Aku malah dikira sok pahlawan.” ujar Ntok.
Sakdani Darmopamudjo mengatakan tahun 1982 Darma Nyata dibuat menjadi bahasa Indonesia. Karena juga sebagian tidak profesional, dalam artian teman-teman (yang bekerja) itu masih merangkap, misalnya merangkap jadi guru dan sebagainya. Yang full ada tapi tidak banyak, terutama penentu-penentu policy orangnya merangkap. Sebenarnya pada tahun itu juga berjalan tapi juga rugi.
Sakdani menuturkan bahwa dia aktif di koran mulai 1965-1966. Sebelumnya dia adalah penulis lepas, pengarang di berbagai majalah, surat kabar. Pertama masuk di Mingguan Andika di Mesen. Pengusahanya namanya Masi Sen seorang Tionghoa, dia juga pengusaha toko emas. Sakdani membuka rubrik Pisungsung berbahasa Jawa. Kemudian Andika pecah menjadi Andika lalu Andika Baru. Sakdani juga mengaku pernah di Mingguan Gelora Berdikari yang terbit bersama Andika tahun 1965-1967.
Gelora Berdikari dulu milik PNI. Pecahnya Andika dan Andika Baru karena manajemennya tidak rukun dan aturan-aturannya tidak kuat. Lalu ada Gelora Berdikari yang tetap terbit, tetapi kemudian tahun 1969 karena ada pemikiran masyarakat terutama masyarakat pecinta bahasa Jawa perlu ada koran berbahasa Jawa. Kemudian lahirlah yang namanya Darmo Kondo.
“Kebetulan saya yang menjadi Pemimpin Redaksi. Tapi itu dilakukan karena adanya kesimpulan, keputusan Musyawarah Kerja Pengarang Sastra Jawa. Yang keputusannya adalah mendirikan koran di Yogya dan Solo. Akhirnya saya kembangkan menjadi Darmo Kondo. Modalnya dari beberapa, tidak hanya dari satu orang tetapi juga dari yayasan. Begitu lahir lalu besar sekali, jumlahnya sampai 33 ribu. Tapi tidak langgeng karena pecah lagi.
Saya (Sakdani) sebagai Pemimpin Redaksi, Pak Tukijo sebagai pemimpin umum tidak cocok dengan manajemen. Unsur-unsurnya ya unsur kurang transparan. Pemimpin Redaksi usianya masih muda yaitu usia 28 tahun. Lalu terjadilah konflik yang akhirnya pecah. Darmo Kondo sendiri saya membuat Darma Nyata. Pemimpin Redaksi nya diganti Pak Maryono yang waktu itu Ketua PWI. Karena dananya lebih, Darma Nyata dapat berkembang sejak tahun 1970 berkembang sampai tahun 1982.”
Dalam perjalanannya hingga mencapai sepuluh tahun, manajemen Harian SOLOPOS oleh informan yang diwawancarai dinilai telah dikelola sebagai mana layaknya sebuah organisasi industri modern.
Sakdani mengatakan, “Yang dimaksud ‘hidup’-nya sebuah media massa itu kan ada hidup yang dalam tanda petik dan juga hidup sesungguhnya. Mingguan Adil itu misalnya, juga Darma Nyata meskipun mampu 28 tahun hidup, tapi hidupnya ya... (seadanya).
Saya (ketika mengelola pers) dikenal teman-teman agak mendingan dalam memberi kesejahteraan. Ada perusahaan pers yang gajinya hanya bisa buat beli es saja. Nah itu pengertian hidup itu kan harus sehat dalam artian yang sebetulnya, karyawan harus sejahtera. Solo bertahun-tahun begitu, karena lahirnya pers di Solo ada ambisi dari orang pers di Solo. SOLOPOS itu menurut saya campuran dari keberhasilan yaitu momennya pas, manajemennya yang lebih baik.
Organisasi yang mengelola pers memang harus seimbang. Kalau kita hanya fokus idealisme, nanti apa yang dipakai buat makan karyawan? Kasarannya kan begitu. Nah sekarang kan banyak teman-teman yang tidak mengindahkan idealisme tadi. Jadi ibarat orang berumah tangga, bukan rasa cinta, kasih sayangnya, tapi seksnya saja. Itu kan harus dipadukan. SOLOPOS sudah melakukan itu.” (Mulyanto Utomo, 2007: 98-99).
Modal usaha
Budaya korporasi profesional yang terbentuk di SOLOPOS bukan terbangun secara serta merta namun melalui proses panjang karena pengaruh komitmen kuat para pendiri lebih khusus lagi para pimpinan. Pengaruh kepemimpinan yang tegas, tanpa kompromi ketika ada pelanggaran telah membentuk budaya disiplin, etos kerja rasa tanggung jawab di tingkat korporasi.
Ketegasan dalam meneggakkan aturan tanpa kompromi ini yang kemudian menimbulkan kepercayaan dari publik. Hal ini pula yang membedakan SOLOPOS dengan koran lain. Budaya kerja seperti ini yang perlu diteruskan dari generasi awal koran ini hingga saat ini dan ke depan. Budaya kerja tersebut salah faktor yang membuat SOLOPOS tetap eksis meski menghadapi para pesaing-pesaingnya.
Seorang akuntan publik di Solo, Rachmad Wahyudi, juga menyebut pengaruh kepemimpinan telah membangun budaya perusahaan dan etos kerja karyawan secara profesional.
“Saya bukan mengagung-agungkan atau melebih-lebihkan seorang Pak Danie (Danie H Soe’oed, Pemred) atau Pak Natur (Bambang Natur Rahadi, Pemimpin Perusahaan), tapi apa yang sudah mereka lakukan itu patut diteladani dan secara jujur harus kita akui eksistensinya," ujar Rachmad.
Mengutip wawancara Harian Kompas dengan Pimred Majalah Berita Mingguan Tempo Goenawan Muhamad yang menyatakan bahwa pers di Indonesia telah berkembang ke arah suatu bisnis, Jakob Oetama berpendapat bahwa pers Indonesia memang telah memasuki fase baru yang dalam pertumbuhannya menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan postur pers masa lalu.
Pers dulu, tambahnya, umumnya hanya terdiri dari redaksi yang hanya menguasai proses produksi berita; mesin cetak milik orang lain, iklan tidak banyak, oplah juga terbatas. Pers sekarang menjadi lembaga yang lengkap; redaksi, percetakan, manajemen (modern). Ada iklan cukup banyak pencapaian oplah di atas 100.000. Penampilan koran dan majalah itu pun modern, bertata warna dan memberikan kesan ditangani secara profesional (Jacob Oetama, 2001: 303).
Berkaca dari Harian Kompas, seperti dipaparkan Jakob Oetama selaku perintis penerbitan koran nomor satu di Indonesia yang terbit mulai 28 Juni 1965 itu, pada awalnya juga dibangun dalam suatu keterbatasan bahkan kesulitan dalam semua bidang, mulai personalia dalam bidang redaksi hingga personalia bidang distribusi.
“Tetapi kesulitan terbesar pada waktu itu adalah percetakan sehingga harus berpindah-pindah. Perubahan politik besar pada tahun 1965 telah membuat distribusi Kompas bisa ditangani sendiri. Tahun 1972 kami memiliki mesin percetakan sendiri berkat tersedianya kredit modal dari bank pemerintah asal sanggup menyediakan sisanya.
Embrio sikap profesionalisme dalam redaksi maupun dalam pengelolaan bisnis berupa sirkulasi, iklan serta pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting tumbuhnya Kompas sejak itu,” terang Jacoeb.
Hal tersebut berarti pula bahwa modal usaha menjadi hal yang sangat penting dalam penerbitan pers modern yang menekankan profesionalisme sebagai landasan usaha. Begitu pula dengan SOLOPOS saat pertama kali dibangun, untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh para dewan pendiri bahwa penerbitan SOLOPOS harus dilaksanakan secara profesional maka perlu dukungan dana yang memadai.
Profesionalisme
Bambang Natur Rahadi selaku Pemimpin Perusahaan Harian SOLOPOS kala itu menyebut bahwa pemodal, dalam hal ini PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit Harian Bisnis Indonesia) memiliki komitmen untuk menerbitkan koran daerah di Solo ini. Artinya, segala kebutuhan finansial yang berkait dengan sumber daya manusia maupun infrastruktur semaksimal mungkin akan dipenuhi.
Dana yang disediakan untuk SOLOPOS waktu itu awalnya no limit (tidak ada batas). Dalam proyeksi anggaran dari bagian keuangan itu sudah dibuat perkiraan dana selama lima tahun. Dan diproyeksikan dalam tempo lima tahun itu SOLOPOS diproyeksi baru untung. Namun karena proyek SOLOPOS berbarengan dengan krisis ekonomi, maka itu menjadi persoalan tersendiri.
Meski awalnya dana untuk SOLOPOS tidak terbatas, kenyataannya setelah jalan bulan ke-7 sudah tidak ada lagi bahasa no limit karena pada saat-saat seperti itu uang sudah menjadi persoalan termasuk di Bisnis Indonesia selaku induk perusahaan SOLOPOS.
“Kalau mau jujur sebetulnya di bulan-bulan ke-6 setelah terbit itu kami sudah mulai kesulitan karena di Jakarta (Bisnis Indonesia) sendiri sudah ribut. Sampai tahun pertama waktu mulai Maret masuk sampai bulan Maret tahun 1998 saya kira sudah lebih dari Rp3 miliar habis. Dan uang Rp3 miliar waktu itu sudah sangat besar,” ungkap Bambang Natur.
Modal menjadi komponen penting dalam industri pers, karena menurut Jakob Oetama realitas yang berkembang dalam sejarah pers di seluruh dunia memang ke arah profesionalisme seperti itu. Jika pers tidak dapat membiayai dirinya dari penghasilan langganan dan iklan –atau dengan kata lain dari usahanya sendiri—maka pers itu harus memperoleh subsidi dari pihak lain; pemerintah, organisasi politik, atau organisasi kepentingan.
Dalam situasi demikian pers akan terhambat perkembangan profesionalisme dan kebebasannya. Pers yang dalam posisi demikian justru tidak akan dapat menjalankan fungsi “kerohaniannya” atau –yang oleh masyarakat pers kita sering disebut—peranan idealnya (Jacob Oetama, 2001: 307).
Presiden Komisaris Kelompok Kompas Gramedia itu berpendapat, pers tidak dibagi-bagikan secara gratis. Surat kabar yang digratiskan akan kehilangan minat pembacanya, karena dianggap kurang bobot kredibilitasnya. Surat kabar dijual, kecuali untuk memenuhi porsi kredibilitasnya, juga karena proses produksinya memerlukan biaya.
Itu berarti bahwa pers sebagai industri harus memperoleh keuntungan yang berfungsi sebagai komponen untuk keberlangsungan hidup surat kabar itu sendiri; sebab jika hanya impas—sementara ongkos-ongkos produksinya cenderung naik—tidaklah mungkin surat kabar itu mempertahankan kehadirannya.
Surat kabar yang dapat hidup dari penghasilannya sendiri akan lebih dapat menjalankan tanggung jawab idealnya dan memelihara kebebasan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara memadai (Jacob Oetama, 2001: 308).
Bersambung.... (*)






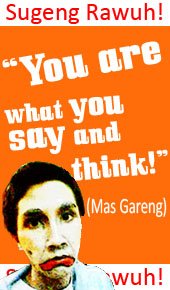



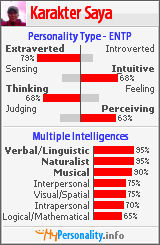









0 komentar:
Posting Komentar