Semarang, 29 April 2009
Memanusiawikan Manusia
Oleh Anindityo Wicaksono
HINGAR-BINGAR deklarasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 tak lama lagi berkumandang. Segera akan kita cicipi bersama manisnya madu janji dan program para pasangan kandidat bersamaan makin mendekatnya pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres).
Dengan mantapnya segera tergelar promosi dengan aneka ragam atribut para calon kepala negara beserta parpol pengusungnya. Wajah-wajah besar mereka akan segera menghiasi berbagai baleho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan bendera di seantero negeri.
Mulai dari jalan protokol hingga sudut-sudut gang berpenerangan temaram. Dari tenda-tenda warung pecel, kios-kios nasi goreng, jendela belakang angkutan umum, bahkan sampai menjadi iklan berjalan di deretan mobil-mobil pikap.
Lantas, ironiskan pemandangan begini, saat mereka seakan habis-habisan terus mencari segala ruang untuk "menjual diri"? Hal ini lazim terjadi dalam dunia politik. Bahkan politik praktis dalam dunia kampus pun mengajarkan demikian.
Bagaimana untuk saling adu strategi, bahkan kalau perlu sampai adu jotos, sikut, dan jegal, guna menarik simpati pendukung dan meraup suara sebanyak-banyaknya dari calon pemilih. Tak ketinggalan tim sukses yang sarat modal akan "jungkir-balik" sebisanya demi sebuah kemenangan.
Dalam kondisi demikian, ada kesan, makna slogan, tulisan, dan serba jargon-jargon politik yang mereka usung dianggap sepi. Terbukti dari betapa asal-asalannya pesan yang mereka kemas dalam semua media kampanye itu. Tampaknya para jurkam ini sadar betul jenis masyarakat bagaimana yang sedang mereka hadapi. Hemat penulis, ada dua alasan penyebab ironi ini.
Pertama, pilpres kekinian hidup dalam masyarakat yang sedang dijangkiti euforia kebebasan demokrasi. Insan-insan yang dipaksa untuk menelan bulat-bulat stigma politik yang terlanjur berkawan karib dengan ajang "adu modal". Artinya, calon pemilih memilih menganut asas manfaat dan hanya akan memilih calon yang paling banyak memberi manfaat (baca: imbalan)
Namun demikian, kecacatan demokrasi yang lama terbentuk di republik ini tidak bisa dipersalahkan pada masyarakat sepenuhnya. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari munculnya rsa ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku parpol dalam tatanan regulasi pemerintahan dan ketatanegaraan.
Harapan akan sosok kepemimpinan yang ideal sudah terkubur dalam-dalam oleh realitas yang bertentangan. Maka sudah jamak jika visi, misi, apalagi kompetensi para calon dianggap sebagai angin lalu.
Kedua, ketidaksehatan demokrasi yang sedang terjadi justru semakin diperparah perilaku kekanak-kanakan para elite politik yang bersaing. Para oknum kian gemar memanipulasi rakyat akibat dimanjakan euforia demokrasi. Mereka lepas dari tanggung jawab pilitik.
Maka tak heran jika setiap kampanye mereka hanya mengerahkan massa; mendanai aksi; lalu setelah berjaya, meninggalkan begitu saja kewajiban dalam memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Makin jauh, politik kita makin tenggelam dalam politik massifikasi massa yang makin miskin substansi.
Memanusiawikan diri
Pada usia belia, Ahmad Wahid (LP3S, 1981) pernah menulis dalam buku hariannya: "Aku ingin bahwa orang memandang dan menilai aku sebagai suatu 'kemutlakan' (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana aku termasuk, serta dari aliran apa aku berangkat. Sekadar memahami manusia sebaagi manusia."
Wahid berani merenungkan dirinya itu "siapa" atau sekadar "apa". Ia memaknai dirinya sebagai "manusia" (human being) yang sedang berproses "memanusiawikan dirinya" (being human). Buah pikirannya kala itu terdesak pencarian jati dirinya sebagai seorang intelektual muda yang gelisah.
Wahid mampu menyadarkan bahwa dirinya pertama-tama tidak dijelaskan oleh namanya, dan tidak oleh pengetahuan dan keterampilannya. Tidak juga oleh pakaian dan kendaraannya, bahkan tidak agamanya. Ia menyadari bahwa ia hanya manusia yang sedang berproses menjadi dirinya sendiri, menaktualisasikan segenap potensi sebagaimana ia diciptakan (dalam Andreas Harefa, 2000).
Kini amat jarang kita jumpai Wahid-Wahid lain di Indonesia. Apalagi mereka yang berkecimpung di ranah politik kekinian. Nampaknya pesona politik memang telah memikat manusia tiada ampun. Muara krisis kepemimpinan masih saja berkutat pada masalah usang: selalu bermulut manis di kala kampanye, lalu setelah terpilih, seenaknya menimpakan setumpuk keserakahan pada rakyatnya.
Kadang saya berpikir, lalu apa gunanya menaruh harapan besar pada pentas demokrasi jika itu hanya berarti seremonial belaka untuk menggantikan "penindas" lama dengan "penindas" baru yang lebih kejam? Sudah saatnya kita, yang merasa lebih cerdas dan melek politik ini, untuk memulai perbaikan kondisi demokrasi bangsa yang kian memprihatinkan.
Untuk menghasilkan pilpres yang ideal demokratis memang tak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan suatu kolaborasi besar di antara seluruh komponen bangsa. Pers, LSM, kaum cerdik-pandai, serta mahasiswa beserta seluruh civitas akademisi sebagai agen perubahan yang diharapkan untuk netral harus hadir di depan menggagas perubahan.
Sinergitas di antara seluruh komponen itu merupakan titik penting eksistensi masyarakat terdidik (civil society) dalam menyongsong pilpres mendatang. Jika tidak, itu berarti sama saja kita sedang mempercepat laju kematian daya kreasi demokrasi untuk lepas dari kemandulan berpikirnya.
(Dimuat di Koran Sore Wawasan, 1 April 2008; dengan penyesuaian)
Memanusiawikan Manusia
Oleh Anindityo Wicaksono
HINGAR-BINGAR deklarasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 tak lama lagi berkumandang. Segera akan kita cicipi bersama manisnya madu janji dan program para pasangan kandidat bersamaan makin mendekatnya pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres).
Dengan mantapnya segera tergelar promosi dengan aneka ragam atribut para calon kepala negara beserta parpol pengusungnya. Wajah-wajah besar mereka akan segera menghiasi berbagai baleho, spanduk, umbul-umbul, poster, dan bendera di seantero negeri.
Mulai dari jalan protokol hingga sudut-sudut gang berpenerangan temaram. Dari tenda-tenda warung pecel, kios-kios nasi goreng, jendela belakang angkutan umum, bahkan sampai menjadi iklan berjalan di deretan mobil-mobil pikap.
Lantas, ironiskan pemandangan begini, saat mereka seakan habis-habisan terus mencari segala ruang untuk "menjual diri"? Hal ini lazim terjadi dalam dunia politik. Bahkan politik praktis dalam dunia kampus pun mengajarkan demikian.
Bagaimana untuk saling adu strategi, bahkan kalau perlu sampai adu jotos, sikut, dan jegal, guna menarik simpati pendukung dan meraup suara sebanyak-banyaknya dari calon pemilih. Tak ketinggalan tim sukses yang sarat modal akan "jungkir-balik" sebisanya demi sebuah kemenangan.
Dalam kondisi demikian, ada kesan, makna slogan, tulisan, dan serba jargon-jargon politik yang mereka usung dianggap sepi. Terbukti dari betapa asal-asalannya pesan yang mereka kemas dalam semua media kampanye itu. Tampaknya para jurkam ini sadar betul jenis masyarakat bagaimana yang sedang mereka hadapi. Hemat penulis, ada dua alasan penyebab ironi ini.
Pertama, pilpres kekinian hidup dalam masyarakat yang sedang dijangkiti euforia kebebasan demokrasi. Insan-insan yang dipaksa untuk menelan bulat-bulat stigma politik yang terlanjur berkawan karib dengan ajang "adu modal". Artinya, calon pemilih memilih menganut asas manfaat dan hanya akan memilih calon yang paling banyak memberi manfaat (baca: imbalan)
Namun demikian, kecacatan demokrasi yang lama terbentuk di republik ini tidak bisa dipersalahkan pada masyarakat sepenuhnya. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari munculnya rsa ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku parpol dalam tatanan regulasi pemerintahan dan ketatanegaraan.
Harapan akan sosok kepemimpinan yang ideal sudah terkubur dalam-dalam oleh realitas yang bertentangan. Maka sudah jamak jika visi, misi, apalagi kompetensi para calon dianggap sebagai angin lalu.
Kedua, ketidaksehatan demokrasi yang sedang terjadi justru semakin diperparah perilaku kekanak-kanakan para elite politik yang bersaing. Para oknum kian gemar memanipulasi rakyat akibat dimanjakan euforia demokrasi. Mereka lepas dari tanggung jawab pilitik.
Maka tak heran jika setiap kampanye mereka hanya mengerahkan massa; mendanai aksi; lalu setelah berjaya, meninggalkan begitu saja kewajiban dalam memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Makin jauh, politik kita makin tenggelam dalam politik massifikasi massa yang makin miskin substansi.
Memanusiawikan diri
Pada usia belia, Ahmad Wahid (LP3S, 1981) pernah menulis dalam buku hariannya: "Aku ingin bahwa orang memandang dan menilai aku sebagai suatu 'kemutlakan' (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana aku termasuk, serta dari aliran apa aku berangkat. Sekadar memahami manusia sebaagi manusia."
Wahid berani merenungkan dirinya itu "siapa" atau sekadar "apa". Ia memaknai dirinya sebagai "manusia" (human being) yang sedang berproses "memanusiawikan dirinya" (being human). Buah pikirannya kala itu terdesak pencarian jati dirinya sebagai seorang intelektual muda yang gelisah.
Wahid mampu menyadarkan bahwa dirinya pertama-tama tidak dijelaskan oleh namanya, dan tidak oleh pengetahuan dan keterampilannya. Tidak juga oleh pakaian dan kendaraannya, bahkan tidak agamanya. Ia menyadari bahwa ia hanya manusia yang sedang berproses menjadi dirinya sendiri, menaktualisasikan segenap potensi sebagaimana ia diciptakan (dalam Andreas Harefa, 2000).
Kini amat jarang kita jumpai Wahid-Wahid lain di Indonesia. Apalagi mereka yang berkecimpung di ranah politik kekinian. Nampaknya pesona politik memang telah memikat manusia tiada ampun. Muara krisis kepemimpinan masih saja berkutat pada masalah usang: selalu bermulut manis di kala kampanye, lalu setelah terpilih, seenaknya menimpakan setumpuk keserakahan pada rakyatnya.
Kadang saya berpikir, lalu apa gunanya menaruh harapan besar pada pentas demokrasi jika itu hanya berarti seremonial belaka untuk menggantikan "penindas" lama dengan "penindas" baru yang lebih kejam? Sudah saatnya kita, yang merasa lebih cerdas dan melek politik ini, untuk memulai perbaikan kondisi demokrasi bangsa yang kian memprihatinkan.
Untuk menghasilkan pilpres yang ideal demokratis memang tak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan suatu kolaborasi besar di antara seluruh komponen bangsa. Pers, LSM, kaum cerdik-pandai, serta mahasiswa beserta seluruh civitas akademisi sebagai agen perubahan yang diharapkan untuk netral harus hadir di depan menggagas perubahan.
Sinergitas di antara seluruh komponen itu merupakan titik penting eksistensi masyarakat terdidik (civil society) dalam menyongsong pilpres mendatang. Jika tidak, itu berarti sama saja kita sedang mempercepat laju kematian daya kreasi demokrasi untuk lepas dari kemandulan berpikirnya.
(Dimuat di Koran Sore Wawasan, 1 April 2008; dengan penyesuaian)






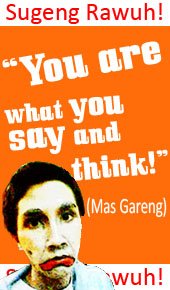



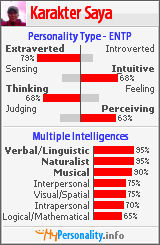









0 komentar:
Posting Komentar