Semarang, 6 Desember 2008
Tirulah Bangsa Jepang
Oleh Anindityo Wicaksono
HARI cerah; jarum jam menunjukkan pukul 8.30. Setelah berdoa pagi dan mandi, saya lalu berangkat kuliah. Kebetulan hari ini saya memang tidak mendapat jadwal liputan. Kepala Biro belum menelepon saya untuk penugasan liputan, seperti janjinya.
Hanya ada satu jadwal kuliah saya hari ini, Kepemimpinan. Dosennya salah satu "dedengkot" di jurusan saya. "Dedengkot" yang saya maksud di sini adalah paling tua, baik dari segi pengalaman mapupun umur. Namanya Soewarso, salah satu pendiri jurusan Administrasi Bisnis, jurusan saya kuliah.
Wajahnya sangar. Kumisnya lebat. Umurnya saya taksir sekitar 45-an tahun. Kata-katanya pun lugas. Dia memang tak suka banyak berbasa-basi, berbicara seperlunya saja.
Namun di balik kesangaran ini, dia bukan termasuk dosen "killer" (pelit nilai), seperti stereotipe yang disematkan pada dosen-dosen senior macam beliau. Beda dengan dosen lain seangkatan beliau seperti Winarti dan Kemi.
Bila ditanya mengenai nilai, jangan tanya "keampuhan" kedua dosen wanita senior di atas dalam hal memberi nilai. Bisa dapat B untuk mata kuliah yang mereka ampu saja, patut dirayakan dengan acara syukuran.
Dalam pertemuan kedua kuliah hari ini, Pak Warso berbicara panjang lebar mengenai teori kepemimpinan. Dari segala aspek yang terkandung di dalamnya hingga sejarah awal-awal kepemimpinan. Menurut dia, merujuk banyak literatur, ternyata ilmu ini termasuk ilmu terapan baru yang baru diakui di akhir abad ke-20. Tepatnya sekitar tahun 1980-an.
Dibandingkan dengan ilmu klasik lainnya macam Sosiologi, Antropologi, Politik, atau ilmu Bumi yang muncul sejak sekitar abad ke-17, Kepemimpinan termasuk ilmu yang baru.
Menurut dia, segala sesuatu dapat dikategorikan ilmu jika mempunyai landasan teori yang telah dibuktikan. Itulah mengapa Kepemimpinan sekarang dapat digolongkan menjadi teori. Sebagai ilmu, katanya, tentunya penerapannya di lapangan dapat menjadi bahan masukan baru bagi perkembangannya. Lalu kondisi di lapangan dapat memberikan "feed-back" yang dapat menyempurnakan teori yang sebelumnya sudah ada.
Tersebut dua versi ilmu kepemimpinan yang saling bertentangan pada masa awal-awalnya. Pertama, teori "Leader is Born". Teori ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan terbentuk. Inilah mengapa di jaman kerajaan dulu kental terbentuk pola patrilinel dalam regenerasi masa pemerintahan raja. Seorang pangeran (anak raja) otomatis berhak menjadi penganti raja jika raja sebelumnya meninggal.
Hak waris ini terlepas dari mampu tidaknya pangeran itu dalam memimpin. Baik dari segi mental maupun secara fisik. Teori ini terlihat pada sebagian besar pola kerajaan di negeri ini, bahkan dunia. Dari jaman kerajaan tertua Kutai, hingga keraton Surakarta dan Yogyakarta, atau Kerajaan Inggris yang masih bertahan hingga sekarang.
Yang kedua, teori "Leader Is Made". Menurut teori ini, pemimpin terbentuk melalui pergulatan sepanjang hidupnya. Jiwa kepemimpinan terbentuk melalui pengalaman hidup langsung di masyarakat. Teori inilah yang berlaku di masyarakat kekinian. Seorang pemimpin yang baik tak lagi seorang yang mempunyai kedekatan biologis dengan penguasa yang lama. Namun seorang yang memiliki kecakapan setelah bersinggungan lansung dengan segala dinamika pergulatan hidup di masyarakat.
Dibanding teori yang pertama, teori ini terasa lebih realistis diterapkan di masa globalisasi seperti sekarang. Lebih-lebih, ketika masyarakat sepakat menjauhkan "nepotisme" apapun bentuknya dari urusan hidup. Pemimpin tak lagi dicetak dari status-quo yang merugikan. Dia harus mampu membuktikan perannya, sebelum nantinya dinilai layak menjadi pemimpin.
Materi yang dibahas dalam kuliah selama satu setengah jam itu sebenarnya cukup menarik. Apalagi banyak bersingungan dengan urusan yang selama ini cukup dekat dengan mahasiswa. Terutama mahasiswa golongan "aktivis" yang akrab dengan idion "pemimpin" ini.
Namun, karena cara penyampaian materi yang hanya searah, para mahasiswa menjadi cepat bosan. Lebih-lebih kini sedang bulan puasa. Gairah beraktivitas yang sudah separuh-napas, dipaksa mendengar ceramah ngalor-ngidul yang tak menarik. Tambah berat lah mata ini untuk melek.
Menurut saya, hal ini harus dijadikan satu bahan evaluasi bagi dosen. Kelas harus sebisanya dibuat bergairah agar murid dapat bersemangat mempelajari serbamateri yang diberikan. Hal ini sudah jamak dipahami ahli komunikasi massa. Sebaik atau sepenting apapun sebuah materi, tak akan dapat mengena sasarannya jika cara penyampaiannya tak menarik. Dosen masakini, terutama FISIP UNDIP--tempat saya berkuliah--harus mulai memikirkan strategi untuk membuat satu pla pengajaran yang lebih menarik.
Menurut Paulo Freire, hakikat sejati "belajar" adalah memerdekakan diri. Murid bukan lah sekadar gelas kosong yang tak berisi sama sekali. Dosen harus tahu benar ini. Paradigma mereka harus diubah. Dari guru tahu segalanya, menjadi murid adalah partner yang seimbang. Namun dalam penerapannya, seringkali kendalanya adalah paham ini bertentangan dengan budaya kita, khususnya budaya Jawa.
 Mendhem Jero
Mendhem Jero
Paham "pendidikan untuk pemerdekaan diri" ala Freire, yang menganggap murid dan guru adalah partner, sangat cocok jika diterapkan di Barat. Di sana, paham liberalisme mendapat porsi besar di masyarakat.
Orang-orang barat hidup dengan sifat egaliter. Artinya, orang tak lagi dihargai atas dasar senioritas ataupun kedudukannya di masyarakat, melainkan kemampuan dan karya seseorang di masyarakat. Hal ini kental terpantul dalam film-film Hollywood. Seorang anak memanggil guru, atau ayahnya sekalipun, hanya dengan namanya.
Bagaimana dengan kita? Budaya Barat ternyata bertolak 180 derajat dengan budaya Indonesia, khususnya Jawa. Budaya seperti bukannya salah, tapi tidak pas jika diterapkan di sini.
Bagi kita, orang Jawa, budaya yang harus tetap dijaga adalah budaya unggah-ungguh (sopan santun), atau ewuh-pakewuh (sungkan). Budaya yang telah ratusan tahun menjadi norma ini mengajarkan kita selalu hormat pada orang tua, apapun kondisinya. Sopan di depan orangtua, tidak neko-neko, serta tidak boleh membantah apalagi mengkritik kejelekan orangtua.
Nilai ini persis dengan sebutan "mendhem jero-mandhap asor" yang populer di jaman Soeharto. Sebagai anak, kita diwajibkan untuk mampu menyimpan keburukan dari orangtua, seburuk apapun itu. Jika tidak, bisa-bisa kita dicap menjadi anak durhaka.
"Kalau kurang ajar sama orangtua, nanti dikutuk jadi kacang mede (buah-buahan sejenis kacang yang bijinya di luar buah)," demikian kata para tetua. Celaka memang. Namun itulah salah satu nilai yang terkandung dalam budaya asli leluhur tanah ini.
Memang, sebagai kaum muda yang dituntut untuk tetap nguri-uri (melestarikan) budaya, kita tak boleh lupa menjunjung budaya kita sendiri. Karena, kalau bukan kita, siapa lagi? Namun bukan berarti budaya ini patut ditelan bulat-bulat.
Sebagai kaum muda dan kaum penerus bangsa, kita harus tetap kritis dan skeptis menerima segala nilai yang ada, entah itu budaya baru atau budaya luhur-adigung peninggalan nenek moyang kita. Idealnya: ambil nilainya yang baik-baik saja, yang jelek kita buang.
Salah satu peran kita adalah membentuk budaya pembaharu yang lebih cocok berlaku di masa kini. Ibarat teknologi, sudah bukan jamannya lagi menggunakan mesin ketik jika sudah ditemukan komputer yang lebih cepat. Sungguh bodoh jika orang masih berkeras menggunakan mesin tik dengan alasan melestarikan budaya.
Apalagi jika alasannya: Sayuti Melik atas suruhan Bung Karno saja menggunakan mesin ketik untuk mengetik naskah proklamasi. Masakan kita melupakan begitu saja jasa beliau dengan meninggalkan mesin ketik?
Bodoh yang menjawab begitu. Pasalnya, perubahan diciptakan demi satu dunia yang lebih baik. Supaya kualitas penghidupan menjadi lebih mudah.
Hal ini sama juga dengan budaya. Nilai-nilai buruk dari budaya bangsa, bukan lah nilai mutlak yang pantang dipertanyakan. Jika budaya ini dirasa menjadi penghambat kemajuan, sudah saatnya kita buang jauh-jauh.
Ada banyak literatur penulis-penulis Eropa yang menyebutkan sifat-sifat buruk bangsa ini. Beberapa di antaranya adalah malas, tak suka bekerja keras, suka berkelahi memperbutkan wilayah/kekuasaan, dan lebih suka berbicara hal-hal remeh ketimbang disuruh berpikir. Benarkah demikian? Tentunya hanya kita yang bisa menilai.
Maka jika Pak Soewarso, atau siapapun itu, mulai membosankan dalam mengajar, adalah tugas kita sebagai mahasiswa untuk mengingatkan. Atau cara yang paling sopan adalah dengan bertanya ketika dibuka sesi pertanyaan. Niscaya kelas akan menjadi lebih hidup dengannya.
 Unggah-Ungguh
Unggah-Ungguh
Kata Stephen Covey, salah satu kebiasaan wajib orang efektif adalah menjadi proaktif. Dia harus berani mengambil peran mengubah keadaan yang dirasakan salah. "Jangan bersikap pasif-reaktif dan menjadi korban keadaan. Orang proaktif harus mampu menyerang sebelum diserang musuh. Keadaan seperti apapun takkan mampu mengubah pendiriannya," begitu tulis Covey.
Penulis ingat cerita teman yang pernah mengikuti kunjungan studi di salah satu universtias swasta di Filipina. Namanya Surachman. Kawanku ini sekarang bekerja di Indomobil Finance, agen pembiayaan khusus merk Suzuki, di Bekasi. Surachman mengakui adanya ketertinggalan atmosfir akademis universitas kita dibanding di Filipina. Khususnya dari sistem pembelajaran di kelas.
Kata dia, mahasiswa di sana tak pernah mencatat ketika di kelas. Ruang kelas, kata dia, adalah tempatnya berdiskusi. Kelas bukan lagi tempatnya mencatat atau melongo mendengarkan dosen "berceramah" atau "berpidato", seperti yang jamak terjadi di banyak perguruan tinggi - khususnya universitas negeri - di sini.
Sebelum pertemuan kuliah, murid sudah diberi rujukan buku yang harus dipelajari. Dosen juga sering memberi tugas resensi alias ringkasan buku yang harus mereka pelajari.
"Minimal sebulan satu buku setiap mata kuliah," kata Rahman.
Itulah mengapa rata-rata kualitas lulusan perguruan tinggi di sana jauh sekali dibandingkan di sini. Dari segi kualitas pengajar pun kita masih kalah jauh. Hampir sebagian besar pengajar program strata-satu (S-1) adalah profesor atau minimal S-2.
Bandingkan dengan rata-rata unibersitas di Indonesia. UNDIP Semarang, misalnya, hingga kini bahkan masih saja ada pengajar yang lulusan S-1. Gelarnya hanya doktorandus (jaman Belanda). Jika begitu, bagaimana bisa mereka dituntut untuk kreatif dalam mengajar? Mengembangkan kualitas internal diri sendiri saja masih malas, apalagi mengurusi kebutuhan intelektual mahasiswa.
Kita harus berubah. Adalah bijak kita hidupi semboyan bapak Presiden SBY yang optimistis itu, menjelang Hari Kemerdekaan 2008: "Indonesia bisa!"
Ya, Indonesia bisa untuk berubah. Syaratnya hanya satu: kita mau! Yakinlah, selama kemauan masih menggebu-gebu, pintu yang tadinya tertutup itu satu-satu akan terbuka lebar membentangkan jalan. Perubahan ini harus menjadi satu kerinduan kita bersama. Ya dosennya, ya muridnya.
Pesan untuk para dosen: jadikanlah kelas sebagai tempat yang penuh pesona. Tempat yang terus membuat kita rindu untuk menyapa ilmu, dan menggugah mahasiswa untuk selalu haus belajar.
Untuk mahasiswa: jadilah proaktif, dinamis, dan penuh antusias dalam kelas. Jangan jadikan budaya "unggah-ungguh" sebagai alasan untuk tak berani berpendapat. Bertanyalah jika dipersilahkan dosen. Jangan pendam kegelisahan intelektualitasmu karena takut pandangan sinis kawan-kawan lain.
Kritis tak selamanya identik dengan pemberontakan ala budaya Barat. Tirulah bangsa Jepang, bangsa Asia yang kian menancapkan kukunya di kancah persaingan-dunia. Mereka bisa kritis dan dinamis, sekaligus tetap menjunjung tinggi budaya leluhur mereka.
Meski terkenal gila-kerja dan senantiasa haus-ilmu, toh kaum muda mereka tak pernah lupa menundukkan kepala jika bertemu dengan orangtua.
Tirulah Bangsa Jepang
Oleh Anindityo Wicaksono
HARI cerah; jarum jam menunjukkan pukul 8.30. Setelah berdoa pagi dan mandi, saya lalu berangkat kuliah. Kebetulan hari ini saya memang tidak mendapat jadwal liputan. Kepala Biro belum menelepon saya untuk penugasan liputan, seperti janjinya.
Hanya ada satu jadwal kuliah saya hari ini, Kepemimpinan. Dosennya salah satu "dedengkot" di jurusan saya. "Dedengkot" yang saya maksud di sini adalah paling tua, baik dari segi pengalaman mapupun umur. Namanya Soewarso, salah satu pendiri jurusan Administrasi Bisnis, jurusan saya kuliah.
Wajahnya sangar. Kumisnya lebat. Umurnya saya taksir sekitar 45-an tahun. Kata-katanya pun lugas. Dia memang tak suka banyak berbasa-basi, berbicara seperlunya saja.
Namun di balik kesangaran ini, dia bukan termasuk dosen "killer" (pelit nilai), seperti stereotipe yang disematkan pada dosen-dosen senior macam beliau. Beda dengan dosen lain seangkatan beliau seperti Winarti dan Kemi.
Bila ditanya mengenai nilai, jangan tanya "keampuhan" kedua dosen wanita senior di atas dalam hal memberi nilai. Bisa dapat B untuk mata kuliah yang mereka ampu saja, patut dirayakan dengan acara syukuran.
Dalam pertemuan kedua kuliah hari ini, Pak Warso berbicara panjang lebar mengenai teori kepemimpinan. Dari segala aspek yang terkandung di dalamnya hingga sejarah awal-awal kepemimpinan. Menurut dia, merujuk banyak literatur, ternyata ilmu ini termasuk ilmu terapan baru yang baru diakui di akhir abad ke-20. Tepatnya sekitar tahun 1980-an.
Dibandingkan dengan ilmu klasik lainnya macam Sosiologi, Antropologi, Politik, atau ilmu Bumi yang muncul sejak sekitar abad ke-17, Kepemimpinan termasuk ilmu yang baru.
Menurut dia, segala sesuatu dapat dikategorikan ilmu jika mempunyai landasan teori yang telah dibuktikan. Itulah mengapa Kepemimpinan sekarang dapat digolongkan menjadi teori. Sebagai ilmu, katanya, tentunya penerapannya di lapangan dapat menjadi bahan masukan baru bagi perkembangannya. Lalu kondisi di lapangan dapat memberikan "feed-back" yang dapat menyempurnakan teori yang sebelumnya sudah ada.
Tersebut dua versi ilmu kepemimpinan yang saling bertentangan pada masa awal-awalnya. Pertama, teori "Leader is Born". Teori ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan terbentuk. Inilah mengapa di jaman kerajaan dulu kental terbentuk pola patrilinel dalam regenerasi masa pemerintahan raja. Seorang pangeran (anak raja) otomatis berhak menjadi penganti raja jika raja sebelumnya meninggal.
Hak waris ini terlepas dari mampu tidaknya pangeran itu dalam memimpin. Baik dari segi mental maupun secara fisik. Teori ini terlihat pada sebagian besar pola kerajaan di negeri ini, bahkan dunia. Dari jaman kerajaan tertua Kutai, hingga keraton Surakarta dan Yogyakarta, atau Kerajaan Inggris yang masih bertahan hingga sekarang.
Yang kedua, teori "Leader Is Made". Menurut teori ini, pemimpin terbentuk melalui pergulatan sepanjang hidupnya. Jiwa kepemimpinan terbentuk melalui pengalaman hidup langsung di masyarakat. Teori inilah yang berlaku di masyarakat kekinian. Seorang pemimpin yang baik tak lagi seorang yang mempunyai kedekatan biologis dengan penguasa yang lama. Namun seorang yang memiliki kecakapan setelah bersinggungan lansung dengan segala dinamika pergulatan hidup di masyarakat.
Dibanding teori yang pertama, teori ini terasa lebih realistis diterapkan di masa globalisasi seperti sekarang. Lebih-lebih, ketika masyarakat sepakat menjauhkan "nepotisme" apapun bentuknya dari urusan hidup. Pemimpin tak lagi dicetak dari status-quo yang merugikan. Dia harus mampu membuktikan perannya, sebelum nantinya dinilai layak menjadi pemimpin.
Materi yang dibahas dalam kuliah selama satu setengah jam itu sebenarnya cukup menarik. Apalagi banyak bersingungan dengan urusan yang selama ini cukup dekat dengan mahasiswa. Terutama mahasiswa golongan "aktivis" yang akrab dengan idion "pemimpin" ini.
Namun, karena cara penyampaian materi yang hanya searah, para mahasiswa menjadi cepat bosan. Lebih-lebih kini sedang bulan puasa. Gairah beraktivitas yang sudah separuh-napas, dipaksa mendengar ceramah ngalor-ngidul yang tak menarik. Tambah berat lah mata ini untuk melek.
Menurut saya, hal ini harus dijadikan satu bahan evaluasi bagi dosen. Kelas harus sebisanya dibuat bergairah agar murid dapat bersemangat mempelajari serbamateri yang diberikan. Hal ini sudah jamak dipahami ahli komunikasi massa. Sebaik atau sepenting apapun sebuah materi, tak akan dapat mengena sasarannya jika cara penyampaiannya tak menarik. Dosen masakini, terutama FISIP UNDIP--tempat saya berkuliah--harus mulai memikirkan strategi untuk membuat satu pla pengajaran yang lebih menarik.
Menurut Paulo Freire, hakikat sejati "belajar" adalah memerdekakan diri. Murid bukan lah sekadar gelas kosong yang tak berisi sama sekali. Dosen harus tahu benar ini. Paradigma mereka harus diubah. Dari guru tahu segalanya, menjadi murid adalah partner yang seimbang. Namun dalam penerapannya, seringkali kendalanya adalah paham ini bertentangan dengan budaya kita, khususnya budaya Jawa.
 Mendhem Jero
Mendhem JeroPaham "pendidikan untuk pemerdekaan diri" ala Freire, yang menganggap murid dan guru adalah partner, sangat cocok jika diterapkan di Barat. Di sana, paham liberalisme mendapat porsi besar di masyarakat.
Orang-orang barat hidup dengan sifat egaliter. Artinya, orang tak lagi dihargai atas dasar senioritas ataupun kedudukannya di masyarakat, melainkan kemampuan dan karya seseorang di masyarakat. Hal ini kental terpantul dalam film-film Hollywood. Seorang anak memanggil guru, atau ayahnya sekalipun, hanya dengan namanya.
Bagaimana dengan kita? Budaya Barat ternyata bertolak 180 derajat dengan budaya Indonesia, khususnya Jawa. Budaya seperti bukannya salah, tapi tidak pas jika diterapkan di sini.
Bagi kita, orang Jawa, budaya yang harus tetap dijaga adalah budaya unggah-ungguh (sopan santun), atau ewuh-pakewuh (sungkan). Budaya yang telah ratusan tahun menjadi norma ini mengajarkan kita selalu hormat pada orang tua, apapun kondisinya. Sopan di depan orangtua, tidak neko-neko, serta tidak boleh membantah apalagi mengkritik kejelekan orangtua.
Nilai ini persis dengan sebutan "mendhem jero-mandhap asor" yang populer di jaman Soeharto. Sebagai anak, kita diwajibkan untuk mampu menyimpan keburukan dari orangtua, seburuk apapun itu. Jika tidak, bisa-bisa kita dicap menjadi anak durhaka.
"Kalau kurang ajar sama orangtua, nanti dikutuk jadi kacang mede (buah-buahan sejenis kacang yang bijinya di luar buah)," demikian kata para tetua. Celaka memang. Namun itulah salah satu nilai yang terkandung dalam budaya asli leluhur tanah ini.
Memang, sebagai kaum muda yang dituntut untuk tetap nguri-uri (melestarikan) budaya, kita tak boleh lupa menjunjung budaya kita sendiri. Karena, kalau bukan kita, siapa lagi? Namun bukan berarti budaya ini patut ditelan bulat-bulat.
Sebagai kaum muda dan kaum penerus bangsa, kita harus tetap kritis dan skeptis menerima segala nilai yang ada, entah itu budaya baru atau budaya luhur-adigung peninggalan nenek moyang kita. Idealnya: ambil nilainya yang baik-baik saja, yang jelek kita buang.
Salah satu peran kita adalah membentuk budaya pembaharu yang lebih cocok berlaku di masa kini. Ibarat teknologi, sudah bukan jamannya lagi menggunakan mesin ketik jika sudah ditemukan komputer yang lebih cepat. Sungguh bodoh jika orang masih berkeras menggunakan mesin tik dengan alasan melestarikan budaya.
Apalagi jika alasannya: Sayuti Melik atas suruhan Bung Karno saja menggunakan mesin ketik untuk mengetik naskah proklamasi. Masakan kita melupakan begitu saja jasa beliau dengan meninggalkan mesin ketik?
Bodoh yang menjawab begitu. Pasalnya, perubahan diciptakan demi satu dunia yang lebih baik. Supaya kualitas penghidupan menjadi lebih mudah.
Hal ini sama juga dengan budaya. Nilai-nilai buruk dari budaya bangsa, bukan lah nilai mutlak yang pantang dipertanyakan. Jika budaya ini dirasa menjadi penghambat kemajuan, sudah saatnya kita buang jauh-jauh.
Ada banyak literatur penulis-penulis Eropa yang menyebutkan sifat-sifat buruk bangsa ini. Beberapa di antaranya adalah malas, tak suka bekerja keras, suka berkelahi memperbutkan wilayah/kekuasaan, dan lebih suka berbicara hal-hal remeh ketimbang disuruh berpikir. Benarkah demikian? Tentunya hanya kita yang bisa menilai.
Maka jika Pak Soewarso, atau siapapun itu, mulai membosankan dalam mengajar, adalah tugas kita sebagai mahasiswa untuk mengingatkan. Atau cara yang paling sopan adalah dengan bertanya ketika dibuka sesi pertanyaan. Niscaya kelas akan menjadi lebih hidup dengannya.
 Unggah-Ungguh
Unggah-UngguhKata Stephen Covey, salah satu kebiasaan wajib orang efektif adalah menjadi proaktif. Dia harus berani mengambil peran mengubah keadaan yang dirasakan salah. "Jangan bersikap pasif-reaktif dan menjadi korban keadaan. Orang proaktif harus mampu menyerang sebelum diserang musuh. Keadaan seperti apapun takkan mampu mengubah pendiriannya," begitu tulis Covey.
Penulis ingat cerita teman yang pernah mengikuti kunjungan studi di salah satu universtias swasta di Filipina. Namanya Surachman. Kawanku ini sekarang bekerja di Indomobil Finance, agen pembiayaan khusus merk Suzuki, di Bekasi. Surachman mengakui adanya ketertinggalan atmosfir akademis universitas kita dibanding di Filipina. Khususnya dari sistem pembelajaran di kelas.
Kata dia, mahasiswa di sana tak pernah mencatat ketika di kelas. Ruang kelas, kata dia, adalah tempatnya berdiskusi. Kelas bukan lagi tempatnya mencatat atau melongo mendengarkan dosen "berceramah" atau "berpidato", seperti yang jamak terjadi di banyak perguruan tinggi - khususnya universitas negeri - di sini.
Sebelum pertemuan kuliah, murid sudah diberi rujukan buku yang harus dipelajari. Dosen juga sering memberi tugas resensi alias ringkasan buku yang harus mereka pelajari.
"Minimal sebulan satu buku setiap mata kuliah," kata Rahman.
Itulah mengapa rata-rata kualitas lulusan perguruan tinggi di sana jauh sekali dibandingkan di sini. Dari segi kualitas pengajar pun kita masih kalah jauh. Hampir sebagian besar pengajar program strata-satu (S-1) adalah profesor atau minimal S-2.
Bandingkan dengan rata-rata unibersitas di Indonesia. UNDIP Semarang, misalnya, hingga kini bahkan masih saja ada pengajar yang lulusan S-1. Gelarnya hanya doktorandus (jaman Belanda). Jika begitu, bagaimana bisa mereka dituntut untuk kreatif dalam mengajar? Mengembangkan kualitas internal diri sendiri saja masih malas, apalagi mengurusi kebutuhan intelektual mahasiswa.
Kita harus berubah. Adalah bijak kita hidupi semboyan bapak Presiden SBY yang optimistis itu, menjelang Hari Kemerdekaan 2008: "Indonesia bisa!"
Ya, Indonesia bisa untuk berubah. Syaratnya hanya satu: kita mau! Yakinlah, selama kemauan masih menggebu-gebu, pintu yang tadinya tertutup itu satu-satu akan terbuka lebar membentangkan jalan. Perubahan ini harus menjadi satu kerinduan kita bersama. Ya dosennya, ya muridnya.
Pesan untuk para dosen: jadikanlah kelas sebagai tempat yang penuh pesona. Tempat yang terus membuat kita rindu untuk menyapa ilmu, dan menggugah mahasiswa untuk selalu haus belajar.
Untuk mahasiswa: jadilah proaktif, dinamis, dan penuh antusias dalam kelas. Jangan jadikan budaya "unggah-ungguh" sebagai alasan untuk tak berani berpendapat. Bertanyalah jika dipersilahkan dosen. Jangan pendam kegelisahan intelektualitasmu karena takut pandangan sinis kawan-kawan lain.
Kritis tak selamanya identik dengan pemberontakan ala budaya Barat. Tirulah bangsa Jepang, bangsa Asia yang kian menancapkan kukunya di kancah persaingan-dunia. Mereka bisa kritis dan dinamis, sekaligus tetap menjunjung tinggi budaya leluhur mereka.
Meski terkenal gila-kerja dan senantiasa haus-ilmu, toh kaum muda mereka tak pernah lupa menundukkan kepala jika bertemu dengan orangtua.






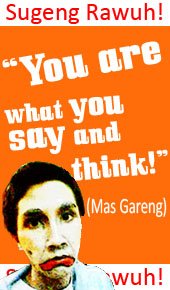



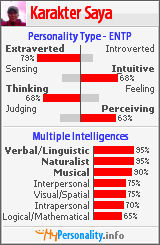









0 komentar:
Posting Komentar