Semarang, 26 Maret 2009
Kutu Loncat
Oleh Anindityo Wicaksono
PEMAHAMAN akan potensi diri ramai digadang-gadang penulis-penulis buku motivasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Dituliskan bahwa kita harus mengetahui kepribadian, minat, dan tingkat kemampuan diri sebelum melangkah memasuki gerbang kehidupan. Bagi mahasiswa, gerbang ini berujung pada realitas yang pelik: dunia kerja.
Pasalnya, dunia kerja adalah kompleksitas yang penuh dengan serba persoalan dan pergulatan. Setidaknya, dengan mengenali diri sendiri--bersamaan dengan pemahaman kemampuan diri--kita dapat memutuskan bidang apa yang menjadi panggilan kita untuk berkarya di kehidupan.
Ada dua contoh cerita teman semasa kuliah saya dulu, Tunggul Joko (25) dan Surrahman (26). Keduanya pintar secara akademis. Mereka meraih gelar sarjana tepat waktu, empat tahun. Hal ini karena ketika kuliah, mereka memfokuskan diri pada kegiatan perkuliahan, tanpa komitmen berarti pada kegiatan-kegiatan ekstra kampus.
Hal ini berarti tak ada waktu di luar perkuliahan mereka yang hilang. Berbeda dengan para aktivis organisasi yang di luar serba tugas dan tuntutan kuliah, masih disibukkan dengan beragam kegiatan pada organisasi yang mereka ikuti.
Joko, misalnya, saat di kampus dia memang pernah turut aktif dalam teater fakultas bersama saya. Namun, entah kenapa, baru sekitar empat bulan bergabung, tiba-tiba dia menghilang. Dia tak pernah lagi terlihat datang pada latihan-latihan selanjutnya.
Suatu ketika saya tanyakan perihal kepergiannya itu. Dengan enteng dijawabnya, "Ah, tidak ada apa-apa. Saya cuma bosan, Dit! Kegiatannya begitu-begitu saja."
Praktis sejak itu, semester tiga, tak ada satupun kegiatan ekstra kampus yang dia ikuti. Dia sempat bekerja menjadi reporter di Koran Sore Wawasan, Semarang. Namun itupun tak lama. Sekitar tiga bulan bekerja, dia keluar dengan alasan tak mampu mengatur waktu. Sejak itu, kerjanya ya cuma bangun-kuliah-pulang-tidur.
Ketika masuk dunia kerja, mulai terdengar betapa seringnya dia berganti-ganti pekerjaan. Setelah lulus, pemuda asal Cilacap yang selama dua semester pernah menimba ilmu di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, ini memulai karirnya dengan menjadi reporter di Harian Suara Pembaruan, Jakarta.
Namun baru dua bulan bekerja, dia keluar. Alasannya? Lagi-lagi bosan. "Setiap hari ada kebaktian untuk para pegawai beragama Nasrani," terangnya, entah serius apa tidak.
Setelah itu dia diterima bekerja di Harian Kontan, Jakarta. Gaji awalnya pun cukup besar untuk seorang bujangan, Rp2,5 juta. Namun baru-baru ini saya dikabari bahwa per Januari 2009 mendatang lagi-lagi dia mengundurkan diri. Alasannya? Ah, sudah tertebak, lagi-lagi bosan. Tak betah? Diiyakannya.
Gorontalo
Teman saya yang kedua, Surrahman, tak jauh berbeda. Rahman, begitu dia biasa dipanggil, langsung hijrah mengadu nasib ke Jakarta begitu lulus. Temanku yang lulus dengan predikat cumlaude ini istimewa. Dia mahasiswa paling kritis di angkatanku.
Selain aktif di lembaga mahasiswa dan acara-acara debat mahasiswa, putra Magelang ini pun giat menulis. Di tingkat akhirnya, dia menjadi salah satu wakil FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, untuk turut dalam kegiatan studi banding mahasiswa Indonesia ke Filipina selama satu bulan.
Dia inilah pemacu, atau kalau tak berlebihan kusebut guruku, dalam menulis. Ini yang paling penting. Jauh sebelum aku mulai gemar menulis dan mengirimkan tulisan-tulisan opiniku pada kolom mahasiswa surat-surat kabar, sudah berulang kali tulisannya dimuat.
Pembahasan dan bahasanya jernih. Kawan ini pulalah yang mengenalkanku pada karya-karya penulis sosialis Indonesia macam Pramoedya Ananta Toer.
Di Jakarta, karir awalnya bermula di Indomobil Finance untuk posisi Management Trainee. Gajinya di atas Rp2 juta. Namun, baru bekerja satu bulan, dia keluar karena diterima di perusahaan manufaktur anak usaha Astra Group. Alasannya ketika itu adalah ingin menambah pengalaman dan mencari suasana kerja yang lebih "bersahabat".
Kelanjutannya mungkin sudah Anda tebak, satu bulan bekerja di perusahaan yang bertempat di Cikarang itu dia menerima panggilan dari PT HM Sampoerna. Alasannya, tak betah. Dia gerah dengan atmosfir kerja di Astra Group yang terlalu kapitalis, istilah dia untuk menggambarkan etos kerja yang superketat.
PT HM Sampoerna ini menempatkannya di Gorontalo untuk posisi pemasaran. Pasar yang masih labil di sana mengharuskan kawanku ini membuka pasar, merebut kue persaingan yang sebelumnya diisi perusahaan-perusahaan rokok lokal.
Saat kutanyakan mengapa dia menerima pekerjaan ini walaupun mengharuskannya pindah di pulau berbentuk huruf "K" ini, "Mumpung masih muda, aku ingin merasakan bekerja di ladang orang, di pulau Sulawesi yang masih asing bagiku."
Awalnya kami, teman-teman seperjuangan kuliahnya, salut dengan kegigihannya merintis kehidupan sampai-sampai nekat merantau ke pulau jauh. Siapa pula yang berani menolak pinangan perusahaan sekelas Sampoerna, perusahaan rokok nomor wahid yang identik dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang tinggi.
Memasuki masa kerja satu bulan, Rahman mulai mengeluhkan pekerjaannya. Posisinya sebagai pemasar yang bertugas memasok produk hingga ke pedagang-pedagang kecil mulai mendapat tantangan. Ada kesalahan dalam manajemennya yang membuat harga yang ditawarkan orang-orang baru seperti Rahman menjadi tak kompetitif. Warung dan pedagang-pedagang kecil lebih memilih agen besar yang berani mematok harga jauh lebih murah.
Seperti umumnya divisi pemasaran, ada target pencapaian yang dibebankan pada tenaga pemasarnya. Perbedaan harga dengan agen besar membuat target per hari Rahman tak pernah tercapai. Dia bahkan bercerita kalau dia mau tak mau harus rela merogoh koceknya sendiri sebesar Rp15 ribu setiap hari untuk menutupi target.
Lebih runyamnya, meski Rahman sudah berulang kali menceritakan kondisi ini, supervisor lapangan seakan masa bodoh. Dia tak pernah mau memahami permasalahan para anak buahnya. Yang utama baginya, target penjualan per hari harus selalu tercapai.
"Kerjanya duduk-duduk saja di kantor ber-AC, tak pernah mau melihat langsung kondisi pasar," gerutu Rahman.
Kondisi ini menjadi dilema baginya. Ingin berganti pekerjaan, tak ada satupun saudara ia miliki di sana. Tapi kalau tidak, bisa-bisa mati muda karena terus menanggung beban moral yang berat.
Sekarang, setelah bekerja belum genap dua bulan di sana, dia memutuskan keluar dan kembali mengadu nasib ke Jakarta. "Lah kalau harus 'tombok" terus Rp15 ribu setiap hari, apa yang kudapat untuk diriku sendiri," ujarnya kesal.
Kutu loncat
Kisah Joko dan Rahman ini menyadarkanku. Dunia kerja memang dunia yang begitu kompleks. Belum terbayangkan sebelumnya, kemampuan dan kepandaian yang menjadi mahkota kesombongan para mahasiswa saat di kampus ternyata menjadi nomor sekian di dunia kerja. Sarjana lulus tepat waktu dengan IPK cumlaude sekalipun, nyatanya masih harus berjibaku dalam kompleksitas dunia kerja yang kejam.
Yang masih susah ditemukan pada lulusan-lulusan sarjana masa kini adalah kegigihan, kata lain keuletan dan ketekunan, atau mentalitas tak kenal menyerah. Banyak lulusan sarjana jaman sekarang yang alpa pada hal ini. Mereka terlalu pongah dengan predikat nilainya, syukur-syukur didapatnya dengan cara yang jujur.
Padahal, bukan orang yang sekadar pintar yang dibutuhkan negeri yang sedang sakit ini. Jumlah orang pintar di republik amburadul ini sudah banyak. Mengutip syair salah satu lagu Iwan Fals, "tak beda dengan roti". Jumlah perguruan tinggi beserta lulusannya terus membludak seiring kenaikan jumlah orang pintar.
Apalagi tak sedikit universitas, baik negeri ataupun swasta sekalipun, yang masih perlu dibenahi kualitasnya di sana-sini. Kualitas pengajar maupun output yang dihasilkannya masih perlu dipertanyakan.
Lihat saja bagaimana universitas-universitas "kacangan" yang mem-branding dirinya layaknya produk sabun mandi makin tumbuh subur. Anda tentu tak asing dengan spanduk-spanduk universitas yang berbunyi: "Lulus 3 tahun", "Satu mahasiswa satu laptop". Sasaran mereka adalah orang-orang yang mendambakan gelar sarjana demi sekadar status dan pengakuan masyarakat. Yang penting punya gelar di belakang nama; isi nol besar.
Yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang adalah orang-orang yang mau berkomitmen tinggi pada bidangnya masing-masing. Yang mau membangun dan mencerahkan secara kontinyu, seberat apapun risikonya. Bukan tipe mental tempe dan kutu loncat yang sedikit-sedikit mengeluh, mengaku tak betah, lalu seenaknya keluar dari pekerjaan untuk memimpikan dunia yang lebih santai.
Kutu loncat adalah sejenis hewan kecil yang oportunis, mendekati apapun yang dapat memberinya keuntungan paling besar. Hidupnya di kepala manusia. Ketika kepala yang ia diami itu tak lagi menguntungkan, atau sudah habis dihisap, loncatlah ia pada kepala lain yang lebih menjanjikan. Masa bodoh ia dengan kerusakan yang sudah ia sebabkan pada sumber penghidupannya yang lama.
Sebagai teman, aku ingin mengutipkan kata-kata Thomas Alva Edisson: "Kesuksesan hanya 1 persen kejeniusan, sisanya, 99 persen, kerja keras." Dalam bahasa Thukul, sang master di bidang ketekunan itu, "Buah kristalisasi keringat tanpa henti." (*)
Kutu Loncat
Oleh Anindityo Wicaksono
PEMAHAMAN akan potensi diri ramai digadang-gadang penulis-penulis buku motivasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Dituliskan bahwa kita harus mengetahui kepribadian, minat, dan tingkat kemampuan diri sebelum melangkah memasuki gerbang kehidupan. Bagi mahasiswa, gerbang ini berujung pada realitas yang pelik: dunia kerja.
Pasalnya, dunia kerja adalah kompleksitas yang penuh dengan serba persoalan dan pergulatan. Setidaknya, dengan mengenali diri sendiri--bersamaan dengan pemahaman kemampuan diri--kita dapat memutuskan bidang apa yang menjadi panggilan kita untuk berkarya di kehidupan.
Ada dua contoh cerita teman semasa kuliah saya dulu, Tunggul Joko (25) dan Surrahman (26). Keduanya pintar secara akademis. Mereka meraih gelar sarjana tepat waktu, empat tahun. Hal ini karena ketika kuliah, mereka memfokuskan diri pada kegiatan perkuliahan, tanpa komitmen berarti pada kegiatan-kegiatan ekstra kampus.
Hal ini berarti tak ada waktu di luar perkuliahan mereka yang hilang. Berbeda dengan para aktivis organisasi yang di luar serba tugas dan tuntutan kuliah, masih disibukkan dengan beragam kegiatan pada organisasi yang mereka ikuti.
Joko, misalnya, saat di kampus dia memang pernah turut aktif dalam teater fakultas bersama saya. Namun, entah kenapa, baru sekitar empat bulan bergabung, tiba-tiba dia menghilang. Dia tak pernah lagi terlihat datang pada latihan-latihan selanjutnya.
Suatu ketika saya tanyakan perihal kepergiannya itu. Dengan enteng dijawabnya, "Ah, tidak ada apa-apa. Saya cuma bosan, Dit! Kegiatannya begitu-begitu saja."
Praktis sejak itu, semester tiga, tak ada satupun kegiatan ekstra kampus yang dia ikuti. Dia sempat bekerja menjadi reporter di Koran Sore Wawasan, Semarang. Namun itupun tak lama. Sekitar tiga bulan bekerja, dia keluar dengan alasan tak mampu mengatur waktu. Sejak itu, kerjanya ya cuma bangun-kuliah-pulang-tidur.
Ketika masuk dunia kerja, mulai terdengar betapa seringnya dia berganti-ganti pekerjaan. Setelah lulus, pemuda asal Cilacap yang selama dua semester pernah menimba ilmu di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, ini memulai karirnya dengan menjadi reporter di Harian Suara Pembaruan, Jakarta.
Namun baru dua bulan bekerja, dia keluar. Alasannya? Lagi-lagi bosan. "Setiap hari ada kebaktian untuk para pegawai beragama Nasrani," terangnya, entah serius apa tidak.
Setelah itu dia diterima bekerja di Harian Kontan, Jakarta. Gaji awalnya pun cukup besar untuk seorang bujangan, Rp2,5 juta. Namun baru-baru ini saya dikabari bahwa per Januari 2009 mendatang lagi-lagi dia mengundurkan diri. Alasannya? Ah, sudah tertebak, lagi-lagi bosan. Tak betah? Diiyakannya.
Gorontalo
Teman saya yang kedua, Surrahman, tak jauh berbeda. Rahman, begitu dia biasa dipanggil, langsung hijrah mengadu nasib ke Jakarta begitu lulus. Temanku yang lulus dengan predikat cumlaude ini istimewa. Dia mahasiswa paling kritis di angkatanku.
Selain aktif di lembaga mahasiswa dan acara-acara debat mahasiswa, putra Magelang ini pun giat menulis. Di tingkat akhirnya, dia menjadi salah satu wakil FISIP Universitas Diponegoro, Semarang, untuk turut dalam kegiatan studi banding mahasiswa Indonesia ke Filipina selama satu bulan.
Dia inilah pemacu, atau kalau tak berlebihan kusebut guruku, dalam menulis. Ini yang paling penting. Jauh sebelum aku mulai gemar menulis dan mengirimkan tulisan-tulisan opiniku pada kolom mahasiswa surat-surat kabar, sudah berulang kali tulisannya dimuat.
Pembahasan dan bahasanya jernih. Kawan ini pulalah yang mengenalkanku pada karya-karya penulis sosialis Indonesia macam Pramoedya Ananta Toer.
Di Jakarta, karir awalnya bermula di Indomobil Finance untuk posisi Management Trainee. Gajinya di atas Rp2 juta. Namun, baru bekerja satu bulan, dia keluar karena diterima di perusahaan manufaktur anak usaha Astra Group. Alasannya ketika itu adalah ingin menambah pengalaman dan mencari suasana kerja yang lebih "bersahabat".
Kelanjutannya mungkin sudah Anda tebak, satu bulan bekerja di perusahaan yang bertempat di Cikarang itu dia menerima panggilan dari PT HM Sampoerna. Alasannya, tak betah. Dia gerah dengan atmosfir kerja di Astra Group yang terlalu kapitalis, istilah dia untuk menggambarkan etos kerja yang superketat.
PT HM Sampoerna ini menempatkannya di Gorontalo untuk posisi pemasaran. Pasar yang masih labil di sana mengharuskan kawanku ini membuka pasar, merebut kue persaingan yang sebelumnya diisi perusahaan-perusahaan rokok lokal.
Saat kutanyakan mengapa dia menerima pekerjaan ini walaupun mengharuskannya pindah di pulau berbentuk huruf "K" ini, "Mumpung masih muda, aku ingin merasakan bekerja di ladang orang, di pulau Sulawesi yang masih asing bagiku."
Awalnya kami, teman-teman seperjuangan kuliahnya, salut dengan kegigihannya merintis kehidupan sampai-sampai nekat merantau ke pulau jauh. Siapa pula yang berani menolak pinangan perusahaan sekelas Sampoerna, perusahaan rokok nomor wahid yang identik dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang tinggi.
Memasuki masa kerja satu bulan, Rahman mulai mengeluhkan pekerjaannya. Posisinya sebagai pemasar yang bertugas memasok produk hingga ke pedagang-pedagang kecil mulai mendapat tantangan. Ada kesalahan dalam manajemennya yang membuat harga yang ditawarkan orang-orang baru seperti Rahman menjadi tak kompetitif. Warung dan pedagang-pedagang kecil lebih memilih agen besar yang berani mematok harga jauh lebih murah.
Seperti umumnya divisi pemasaran, ada target pencapaian yang dibebankan pada tenaga pemasarnya. Perbedaan harga dengan agen besar membuat target per hari Rahman tak pernah tercapai. Dia bahkan bercerita kalau dia mau tak mau harus rela merogoh koceknya sendiri sebesar Rp15 ribu setiap hari untuk menutupi target.
Lebih runyamnya, meski Rahman sudah berulang kali menceritakan kondisi ini, supervisor lapangan seakan masa bodoh. Dia tak pernah mau memahami permasalahan para anak buahnya. Yang utama baginya, target penjualan per hari harus selalu tercapai.
"Kerjanya duduk-duduk saja di kantor ber-AC, tak pernah mau melihat langsung kondisi pasar," gerutu Rahman.
Kondisi ini menjadi dilema baginya. Ingin berganti pekerjaan, tak ada satupun saudara ia miliki di sana. Tapi kalau tidak, bisa-bisa mati muda karena terus menanggung beban moral yang berat.
Sekarang, setelah bekerja belum genap dua bulan di sana, dia memutuskan keluar dan kembali mengadu nasib ke Jakarta. "Lah kalau harus 'tombok" terus Rp15 ribu setiap hari, apa yang kudapat untuk diriku sendiri," ujarnya kesal.
Kutu loncat
Kisah Joko dan Rahman ini menyadarkanku. Dunia kerja memang dunia yang begitu kompleks. Belum terbayangkan sebelumnya, kemampuan dan kepandaian yang menjadi mahkota kesombongan para mahasiswa saat di kampus ternyata menjadi nomor sekian di dunia kerja. Sarjana lulus tepat waktu dengan IPK cumlaude sekalipun, nyatanya masih harus berjibaku dalam kompleksitas dunia kerja yang kejam.
Yang masih susah ditemukan pada lulusan-lulusan sarjana masa kini adalah kegigihan, kata lain keuletan dan ketekunan, atau mentalitas tak kenal menyerah. Banyak lulusan sarjana jaman sekarang yang alpa pada hal ini. Mereka terlalu pongah dengan predikat nilainya, syukur-syukur didapatnya dengan cara yang jujur.
Padahal, bukan orang yang sekadar pintar yang dibutuhkan negeri yang sedang sakit ini. Jumlah orang pintar di republik amburadul ini sudah banyak. Mengutip syair salah satu lagu Iwan Fals, "tak beda dengan roti". Jumlah perguruan tinggi beserta lulusannya terus membludak seiring kenaikan jumlah orang pintar.
Apalagi tak sedikit universitas, baik negeri ataupun swasta sekalipun, yang masih perlu dibenahi kualitasnya di sana-sini. Kualitas pengajar maupun output yang dihasilkannya masih perlu dipertanyakan.
Lihat saja bagaimana universitas-universitas "kacangan" yang mem-branding dirinya layaknya produk sabun mandi makin tumbuh subur. Anda tentu tak asing dengan spanduk-spanduk universitas yang berbunyi: "Lulus 3 tahun", "Satu mahasiswa satu laptop". Sasaran mereka adalah orang-orang yang mendambakan gelar sarjana demi sekadar status dan pengakuan masyarakat. Yang penting punya gelar di belakang nama; isi nol besar.
Yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang adalah orang-orang yang mau berkomitmen tinggi pada bidangnya masing-masing. Yang mau membangun dan mencerahkan secara kontinyu, seberat apapun risikonya. Bukan tipe mental tempe dan kutu loncat yang sedikit-sedikit mengeluh, mengaku tak betah, lalu seenaknya keluar dari pekerjaan untuk memimpikan dunia yang lebih santai.
Kutu loncat adalah sejenis hewan kecil yang oportunis, mendekati apapun yang dapat memberinya keuntungan paling besar. Hidupnya di kepala manusia. Ketika kepala yang ia diami itu tak lagi menguntungkan, atau sudah habis dihisap, loncatlah ia pada kepala lain yang lebih menjanjikan. Masa bodoh ia dengan kerusakan yang sudah ia sebabkan pada sumber penghidupannya yang lama.
Sebagai teman, aku ingin mengutipkan kata-kata Thomas Alva Edisson: "Kesuksesan hanya 1 persen kejeniusan, sisanya, 99 persen, kerja keras." Dalam bahasa Thukul, sang master di bidang ketekunan itu, "Buah kristalisasi keringat tanpa henti." (*)






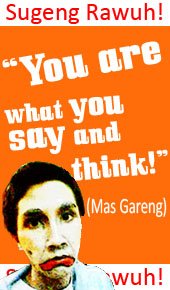



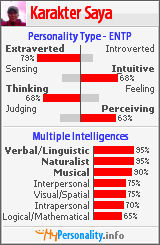









0 komentar:
Posting Komentar